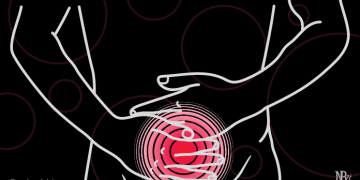Mubadalah.id – Bencana longsor dan banjir bandang Sumatra masih meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam. Di media sosial belakangan ini, muncul kabar masyarakat korban bencana terpaksa memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa arus untuk membangun rumah darurat dan jembatan sementara. Mereka gotong royong dalam memproses pengolahan kayu gelondongan hasil pembalakan liar tersebut.
Dalam sosiologi lingkungan, fenomena ini dijelaskan oleh teori “resiliensi komunitas” dari pakar seperti C.S. Holling, di mana masyarakat pascabencana beradaptasi dengan sumber daya lokal untuk membangun ketahanan sosial-ekologis. Pendekatan ini juga selaras dengan teori “gotong royong” Clifford Geertz dalam antropologi Indonesia, yang menekankan solidaritas desa untuk rekonstruksi mandiri.
Pertanyaannya kemudian, dimana peran pemerintah? Usaha apa yang akan pemerintah lakukan untuk membangun kembali rumah-rumah warga dan infrastruktur yang hancur? Langkah apa yang akan pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta pertanyaan lain seringkali menggelayuti pikiran saya.
Bayangkan, korban bencana yang meninggal sudah di angka seribu lebih, ratusan orang hilang, ribuan lainnya luka-luka. Banyak rumah hancur bahkan hilang, ada banyak desa yang tertimbun lumpur setebal 1-2 meter. Dan, banyak akses jalan rusak parah, hingga orang-orang yang kehilangan anak-anaknya, orang tuanya, dan lain-lain. Untuk membangun kembali kehidupan yang normal, mereka tak bisa berjuang sendiri.
Di tengah ketidakpastian bantuan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat pun berinisiatif menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi secara mandiri. Fenomena warga yang secara mandiri mengolah kayu gelondongan menunjukkan kreativitas luar biasa dalam menghadapi keterbatasan bantuan resmi, di mana gotong royong menjadi pondasi utama untuk bertahan hidup.
Insiatif Swadaya
Fenomena ini juga mencerminkan keputusasaan warga di tengah keterlambatan bantuan pemerintah, di mana mereka terpaksa mencari solusi sendiri pasca-rumah dan infrastruktur hancur lebur. Beban ini semakin memperberat korban bencana yang sudah kehilangan segalanya.
Alih-alih meringankan, inisiatif swadaya ini justru membebani warga yang harus bekerja keras mengangkut, mengolah, dan merakit kayu di tengah lumpur dan keterbatasan alat. Tanpa bantuan teknis atau logistik dari pemerintah, proses ini berisiko tidak aman. Seperti jembatan darurat yang rawan roboh atau rumah sementara yang tak tahan cuaca. Hal ini menunjukkan kegagapan respons bencana, memaksa korban menjadi “insinyur” dadakan.
Soal solusi mandiri dari masyarakat, saya jadi teringat dengan fenomena yang terjadi di kampung halaman saya. Jika Anda berkunjung ke daerah di Pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan, Anda akan menemukan banyak rumah yang sudah ditinggal penghuninya karena rumah sudah terendam air. Anda juga akan melihat banyak rumah yang lantainya sudah warga tinggikan.
Fenomena Meninggikan Lantai Rumah
Fenomena meninggikan lantai rumah (menguruk rumah) menjadi pemandangan biasa di daerah rawan banjir seperti Jakarta, Pekalongan, Semarang, atau pesisir Jawa. Keluarga saya termasuk yang mengikuti tren ini. Sebab, di mata masyarakat hal semacam ini seperti sudah dinormalisasikan. Masyarakat seakan pasrah atas terjadinya banjir tahunan.
Tiap tahun, banyak rumah warga akan terendam banjir saat musim hujan. Banjir disebabkan oleh saluran air atau drainase yang sudah tidak berfungsi lagi, di samping penurunan tanah yang terjadi tiap tahun. Warga pun menempuh solusi jangka pendek, yakni meninggikan lantai rumah. Sementara, pemerintah hanya bisa meninggikan jalan.
Di wilayah lain, saya yakin ribuan keluarga juga memilih meninggikan lantai rumah mereka hingga setinggi 30 cm hingga 1 meter, bahkan lebih, demi menghindari air banjir yang datang tanpa permisi. Baik banjir yang diakibatkan sistem drainase yang buruk atau banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir. Pertanyaan pun muncul, mengapa rakyat harus berjuang sendiri sementara pemerintah gagal mengatasi akar masalah banjir?
Fenomena ini bukan hal baru. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2024 saja, lebih dari 1,2 juta unit rumah di Indonesia terdampak banjir, dengan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Di Jakarta Utara, misalnya, warga Kampung Marunda sudah biasa meninggikan rumah sejak 2010-an.
Mereka membangun sendiri, tanpa bantuan pemerintah, menggunakan besi beton dan cor semen sederhana. Biayanya? Antaranya Rp 40-70 juta per rumah, setara dengan biaya hidup satu tahun bagi keluarga kelas bawah.
Dampak Deforestasi dan Banjir yang Berulang
Normalisasi ini ironis. Masyarakat, yang seharusnya menjadi korban, malah terpaksa jadi “pahlawan” solusi sendiri. Biaya untuk meninggikan rumah seharusnya bisa terpakai untuk kebutuhan lain. Sayangnya, pemerintah kita tidak bisa mengatasi akar masalah banjir. Pemerintah kerap menyalahkan cuaca ekstrem, tapi fakta lapangan menunjukkan ketidakbecusan kronis.
Tidak perlu jauh-jauh untuk melihat fakta ke belakang. Yang baru terjadi saja, yakni banjir bandang yang menghantam sebagian Pulau Sumatra, akibat kesalahan pemerintah terutama terkait tata kelola lingkungan dan izin usaha, lemahnya pengawasan, hingga lemahnya penegakan hukum. Hal ini memicu terjadinya deforestasi.
Singkatnya, bencana yang “hanya mencekam di medsos” menurut Kepala BNPB ini merupakan dampak dari ‘bersatunya’ kepentingan bisnis dan politik dalam penguasaan sumber daya alam.
Di banyak kasus, alih-alih menangani penyebab utama seperti pembangunan liar di bantaran sungai, konversi lahan resapan air menjadi permukiman dan gedung-gedung bertingkat, serta pengelolaan sampah yang buruk, respons pemerintah lebih sering terfokus pada solusi reaktif seperti pompa air darurat dan bantuan pasca-bencana.
Akibatnya, banjir berulang setiap musim hujan, merugikan ekonomi warga dan mengancam nyawa ribuan warga, sementara rencana jangka panjang seperti masterplan penanggulangan banjir kerap terhambat korupsi, birokrasi lambat, dan kurangnya koordinasi antar-daerah.
Lebih dalam lagi, pemerintah gagal menangani isu sosial-ekonomi yang memperburuk banjir, seperti tingginya produksi sampah masyarakat dan praktik illegal logging yang dilakukan oknum perusahaan.
Selain itu, tidak adanya program rehabilitasi hutan berbasis masyarakat, penegakan hukum ketat terhadap pelanggar tata ruang, serta integrasi perubahan iklim dalam perencanaan nasional membuat banjir berulang menjadi bom waktu. Pada akhirnya, ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan struktural negara dalam memprioritaskan kepentingan publik di atas oligarki properti dan industri ekstraktif.
Beban Ekonomi yang Tak Ringan
Ketidakbecusan pemerintah mengatasi akar masalah banjir di berbagai titik memaksa warga untuk meninggalkan rumah-rumah mereka. Meski demikian, ada juga yang masih memilih bertahan tinggal di desa dengan cara meninggikan lantai rumah.
Meninggikan lantai rumah tampak solutif, tapi bayarannya mahal. Biaya utama datang dari material: semen, pasir, besi, dan tenaga tukang. Total pengeluaran bisa berpuluh-puluh juta tergantung kebutuhan. Bagi warga miskin, ini berarti mereka harus gadai sertifikat rumah atau tambah jam kerja. Survei Lembaga Penelitian Ekonomi (LPE) UI menemukan, 60% keluarga rawan banjir alokasikan 40% pendapatan untuk adaptasi ini, memicu utang jangka panjang.
Warga miskin yang tinggal di kawasan rawan banjir sering kali menghadapi beban ekonomi berat akibat genangan air yang datang berulang kali. Setiap musim hujan, mereka kehilangan harta benda seperti perabot rumah tangga, stok makanan, dan alat kerja sederhana yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari, sehingga biaya penggantian mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah yang sulit dipenuhi dari pendapatan harian minim.
Kerugian pendapatan semakin parah karena banjir menghentikan aktivitas usaha kecil seperti jualan keliling atau buruh harian, sementara biaya kesehatan melonjak akibat penyakit seperti diare dan infeksi kulit yang menyerang anak-anak. Tanpa tabungan atau akses kredit murah, mereka terpaksa berutang ke rentenir dengan bunga tinggi, yang memperburuk siklus kemiskinan dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
Kegagalan Sistemik
Lebih parah lagi, di desa-desa daerah pesisir jawa, sawah subur yang jadi andalan petani berubah jadi lautan lumpur tak berharga, dan tambak udang milik nelayan hancur lebur. Kondisi ini merenggut pekerjaan musiman yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Akibatnya, tingkat pendapatan menurun, anak-anak sulit bayar sekolah, dan migrasi ke kota besar kian masif, meninggalkan desa-desa yang semakin sepi dan rapuh.
Fenomena ini bukti kegagalan sistemik. Banjir bukan takdir, tapi akibat konversi lahan hijau jadi beton, hilangnya resapan air, penggundulan hutan, pembangunan liar tanpa perencanaan drainase memadai, mengeruk sumber daya alam berlebihan, korupsi dalam proyek penanganan banjir, dan lain-lain. Pertanyaan dasar pun muncul, mau sampai kapan kita menguruk rumah?
Fenomena meninggikan lantai rumah populer karena kebutuhan mendesak, tapi jangan sampai jadi normalisasi ketidakberesan pemerintah. Rakyat sudah cukup bayar pajak, saatnya pejabat kerja nyata. Jika kita biarkan, bukan lantai rumah saja yang tinggi, tapi juga tumpukan keluhan dan utang. []