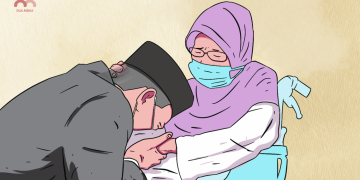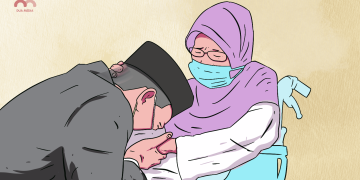Mubadalah.id – Masyarakat Indonesia merayakan Hari Ibu setiap 22 Desember. Presiden Soekarno pertama kali menetapkan peringatan ini pada tahun 1953 bukan sekadar untuk mengapresiasi kerja domestik perempuan. Sebaliknya, peringatan ini bertujuan menghidupkan kembali memori kolektif tentang Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung pada 22 Desember 1928.
Kala itu, para Ibu dengan lantang menyuarakan isu perkawinan anak, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan penolakan poligami. Sejarah masyhur yang harus terus kita ingat bahwa Ibu-Ibu Indonesia pernah mengukir catatan revolusioner untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Namun, jika kita melihat realitas hari ini, ada semacam ingatan yang terlupakan antara sejarah tersebut dengan cara kita merayakannya. Hari Ibu telah mengalami penyempitan makna. Dari sebuah peringatan gerakan politik dan intelektual, menjadi sekadar perayaan sentimental yang bersifat privat. Kenapa hal ini bisa terjadi?
Jejak Domestikasi dan Warisan Orde Baru
Reduksi makna ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan melalui konstruksi politik yang sistematis. Pada masa pemerintahan Orde Baru, negara memainkan peran besar dalam mendefinisikan siapa itu “perempuan ideal”. Melalui ideologi yang sering kita sebut para sosiolog sebagai “Ibuisme Negara”, peran perempuan terkunci rapat-rapat di ranah domestik.
Menurut Julia Suryakusuma dalam bukunya yang berjudul Ibuisme Negara, pada masa Orde Baru perempuan acap kali terposisikan sebagai pendamping suami (melalui organisasi seperti Dharma Wanita) dan pengelola rumah tangga (melalui PKK).
Orde Baru mengubah wajah Hari Ibu yang semula merayakan kemandirian politik perempuan menjadi alat untuk mempertegas peran domestik sebagai penjaga stabilitas keluarga. Narasi ini mengukur keberhasilan perempuan hanya dari kepatuhan kepada suami dan kemampuan mendidik anak demi pembangunan nasional. Dampaknya, penguasa secara sengaja memadamkan semangat kritis Kongres Perempuan 1928 yang menuntut hak sipil dan politik.
Depolitisasi dan Pengaburan Sejarah
Lebih jauh lagi, terjadi upaya depolitisasi gerakan perempuan pasca-peristiwa 1965. Organisasi perempuan yang kritis dan radikal dibubarkan atau tercitrakan buruk. Untuk memastikan tidak ada lagi gerakan perempuan yang berani menggugat kebijakan negara, makna Hari Ibu pun terpoles dan terbatas pada narasi peran domestik dan apolitis.
Alih-alih membicarakan hak-hak buruh perempuan atau keterwakilan perempuan di parlemen, perayaan Hari Ibu berganti dengan lomba memasak, merias wajah, atau sekadar pemberian bunga. Sejarah tentang Nn. Sujatin Kartowiyono atau Siti Munijah yang berpidato tentang martabat bangsa di podium kongres pun terkubur di bawah tumpukan kartu ucapan “Selamat Hari Ibu” yang manis namun kosong akan nilai perjuangan.
Konsep Kesalingan dan Upaya Menghentikan Domestikasi
Pengaburan makna sejarah tentang Hari Ibu sebetulnya ada dalam satu muara dengan tujuan untuk membatasi perempuan hanya dalam ranah domestik. Maka dari itu, penting kiranya untuk menghentikan konsep domestikasi sebagai wadah yang memenjarakan potensi perempuan. Konsep kesalingan atau mubadalah sebagaimana yang sering disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah cara pandang yang relevan untuk mencapai keadilan.
Perspektif Mubadalah mengubah cara kita melihat relasi laki-laki dan perempuan dari kacamata hierarki menjadi kemitraan sejajar yang saling menopang. Alih-alih terjebak dalam dikotomi siapa yang melayani dan dilayani, prinsip ini memosisikan keduanya sebagai rekan yang setara dalam setiap aspek kehidupan.
Berbeda dengan domestikasi Orde Baru yang memaksakan peran tunggal perempuan di rumah, konsep kesalingan tidak terlepas dari tujuan keadilan hakiki. Paradigma ini menekankan bahwa tanggung jawab merawat kehidupan rumah tangga sekaligus membangun peradaban di ruang publik merupakan mandat kemanusiaan yang harus laki-laki dan perempuan pikul bersama.”
Mengadopsi semangat kesalingan berarti berhenti memandang kerja domestik sebagai beban kodrati yang hanya melekat pada tubuh perempuan. Ketika urusan rumah tangga dan pengasuhan anak disadari sebagai tanggung jawab kolektif, maka pintu bagi perempuan untuk kembali ke “khitah” pergerakan 1928 akan terbuka lebar. Perempuan tidak lagi harus merasa bersalah ketika ia memilih untuk berpolitik, berorganisasi, atau berkarya, karena ia tidak lagi berjuang sendirian dalam ruang privat yang timpang.
Mengembalikan Hari Pergerakan Perempuan Indonesia
Dengan menghentikan domestikasi melalui prinsip kesalingan, kita sedang mengembalikan martabat perempuan Indonesia sebagai subjek penuh dalam sejarah. Hari Ibu bukan lagi menjadi hari kasih sayang dan penghargaan sehari, melainkan momentum yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar bangsa ini selalu melibatkan tangan-tangan perempuan yang berdaulat.
Kesalingan menuntut kita untuk saling memanusiakan, saling mendukung peran satu sama lain, dan memastikan bahwa tidak ada lagi perempuan yang suaranya dibungkam atas nama “tugas rumah tangga”.
Pada akhirnya, apa yang sebetulnya kita rayakan setiap 22 Desember adalah sebuah keberanian. Keberanian para perempuan tahun 1928 yang melampaui batas zamannya untuk menuntut hak-hak sipil, politik, dan kemanusiaan.
Sudah saatnya kita berhenti mereduksi Hari Ibu menjadi sekadar perayaan sentimental. Sudah saatnya kita merebut kembali esensi Hari Ibu sebagai Hari Pergerakan Perempuan Indonesia.
Melalui narasi ini, kita menegaskan bahwa keadilan sosial menuntut keterlibatan perempuan sebagai subjek yang berdaulat. Kita harus membebaskan perempuan dari keterbatasan ruang domestik, memuliakan mereka dalam prinsip kesalingan, dan mengakui peran mereka sebagai motor penggerak perubahan bangsa. []