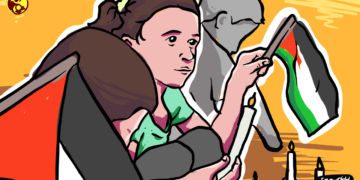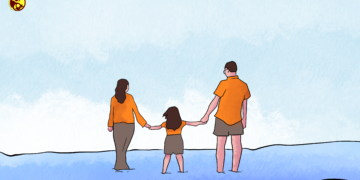Penemuan dan Pengingkaran
Ayaan Hirsi Ali bukanlah perempuan biasa, ia lahir dari orang tua yang memiliki tingkat literasi cukup tinggi. Di usia sekolah dasar dia sudah menguasai beberapa bahasa; Somali, Arab, Amharic (Ethiopia), Swahili (Kenya), dan Inggris. Ketika remaja, dia sangat gemar membaca karya sastra dari novel klasik Inggris, misalnya: 1984, Adventures of Huckleberry Finn, The Thirty- Nine Steps, hingga novel-novel Rusia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Ayaan tidak hanya gemar membaca buku, sebagai anak seorang politisi, Ayaan sudah terbiasa mendengarkan diskusi-diskusi ‘tema berat’, termasuk soal permasalahan-permasalan sosial politik yang terjadi. Dengan latar belakang seperti itu, wajar jika dia memiliki cara berpikir kritis, termasuk dalam beragama. Orang-orang seperti ini akan lebih tepat jika bertemu dengan pandangan-pandangan keagamaan yang –meminjam bahasa Mas Ulil Absar Abdalla — ‘intelek’.
Sayangnya, dari pengalaman yang saya ceritakan di atas, Ayaan justru mengalami pengalaman-pengalaman keberIslaman yang menurutnya tidak rasional dan bahkan cenderung tidak manusiawi. Ketika dia aktif di kelompok-kelompok Muslim Brotherhood di Kenya, yang karena terinspirasi oleh ajakan Sayyid Qutb, mereka mengajak untuk bergerak, berjihad melawan Yahudi dan ‘’Barat”, padahal Ayaan yang sejak kecil gemar melahap buku-buku karya pengarang Inggris dan Amerika merasa tidak menemukan kejahatan di sana, justru dari buku-buku tersebut dia menemukan ‘moral’ dan penghormatan kepada pilihan individu.
Propaganda negatif terhadap Barat oleh orang-orang muslim yang ia dengar ketika di Saudi, Somalia dan Kenya dapat dipatahkan saat ia mendarat di Eropa, Jerman dan kemudian sampai di Belanda. Ayaan melarikan diri dari perjodohan, dari perampasan pilihan pribadi. Di Belanda, ia menemukan sebenar-benar kehidupan yang selama ini ia imajinasikan, terutama sebagai perempuan. Ketika bepergian tanpa didampingi laki-laki, ia tidak harus was-was ditikam dari belakang dengan pisau menghunus ke leher seperti pengalamannya ketika di Somalia.
Di Belanda ia menyaksikan hukum benar-benar ditegakkan, misalnya ketika ia lupa memasang lampu sepedanya di malam hari dan kemudian ditilang oleh polisi tanpa ditarik pungli. Negara benar-benar hadir, terutama bagi mereka yang membutuhkan, bahkan bagi refugee (pengungsi) seperti dirinya dan ribuan lainnya.
Ayaan, yang pernah mengalami langsung tinggal beberapa saat di pengungsian Somalia, cukup kaget ketika melihat lokasi ‘barak’ pengungsi di Belanda yang cukup bagus dan sangat manusiawi, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pengalaman di barak pengungsian sebelumnya yang tidak manusiawi, terutama pada perempuan dan anak-anak.
Ayaan yang selalu menuntut hak individu sebagai perempuan merasa mendapat angin segar ketika berada di negara yang menjamin kebebasan hak untuk setiap penduduknya. Ia selalu mendapat dukungan dari negara untuk memenuhi mimpi-mimpinya, salah satunya dengan melanjutkan kuliah di jurusan ilmu politik, Leiden Univeristy.
Di sana dia semakin menemukan pemuas dahaga pengetahuannya. Ia melahap buku-buku tentang pemerintahan, negara, sistem politik, sejarah Belanda dan Eropa, dll; semua itu ia pelajari untuk mengurai aspek-aspek yang membuat suatu bangsa memiliki kondisi yang berbeda dengan lainnya.
Bacaan-bacaannya yang semakin kaya menantang keimanannya sebagai seorang muslim. Misalnya ketika mendapati pendapat Darwin yang menganggap bahwa sejarah penciptaan adalah dongeng belaka, sementara Freud mengatakan bahwa kita harus berkuasa atas diri sendiri. Spinoza meyakini bahwa tidak ada malaikat, keajaiban, tidak perlu berdoa kepada apapun di luar diri kita; Tuhan adalah kita dan alam. Apalagi ketika Emil Durkheim memprovokasi bahwa manusia itu mengimajinasikan agama untuk memberikan rasa aman bagi diri mereka. Makin goyahlah iman Ayaan.
Kepercayaannya kepada Islam mulai pudar, ketika di Belanda, ia masih saja menemukan perempuan-perempuan muslim (Somalia) menjadi korban kekerasan pasangannya. Selain kuliah di Leiden, perempuan yang dengan mudah belajar bahasa Belanda ini bekerja untuk asylum center sebagai penerjemah resmi untuk para refugee Somalia. Sebagai penerjemah, ia banyak mendengar langsung kisah-kisah pilu dan kasus-kasus para calon refugee dan refugee yang sebagian besar tentang pemerkosaan, kekerasan, dan pelecehan seksual.
Kasus yang sangat umum adalah suami-suami yang menghabiskan uang untuk mengkonsumsi qat (dedaunan dari Arabian yang memiliki zat adiktif semacam rokok, dan sangat lazim dikonsumsi laki-laki Somalia), ketika istri menyembunyikan uang tersebut, mereka akan memukul istrinya sampai kemudian polisi mengintervensi dan tentu membutuhkan bantuan Ayaan sebagai penerjemah.
Kisah-kisah lain dari refugee Somalia yang membuat Ayaan semakin ‘emosi’ terhadap Islam adalah ketika mendapati perempuan-perempuan yang menerima kekerasan dari suami dan menganggapnya sebagai takdir Allah; jika mereka bersabar, penderitaannya akan dihapuskan.
Begitupun alasan-alasan perempuan yang enggan meminta bantuan keluarga ketika mendapat kekerasan dari suami, menurutnya keluarga pasti akan membela suami mereka, karena suami memang diperbolehkan memukul istri mereka ketika istri dianggap ‘misbehave’, dan itu tercatat dalam Quran. Menurut Ayaan, perempuan Belanda juga banyak yang dianiaya, tetapi komunitas dan keluarga mereka tidak akan menerima hal tersebut, apalagi atas nama agama.
Kasus –kasus tersebut sangat kontras dengan apa yang Ayaan temui pada keluarag Johanna, mentor bahasa belandanya. Johanna dan suaminya, Marten merupakan pasangan yang Ayaan imajinasikan. Sebagai seorang suami, Marten bukanlah ‘boss’ rumah tangga, mereka mendiskusikan apapun bersama. Mereka bahkan melibatkan kedua anak-anaknya dalam diskusi dan dibolehkan memberi interupsi; mereka berdua saling meminta saran. Marten juga tidak enggan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga.
Yang paling membuatnya nyaman dengan Johanna adalah ketika Ayaan menyampaikan penyesalannya dan menganggap diri ‘egois’ karena harus mendahulukan keinginananya ketimbang kehendak orang tuanya. Bagi Johanna, itu bukanlah kesalahan, karena semua orang berhak mengejar kebahagia personalnya. Sementara dalam ajaran Islam yang Ayaan terima, umat muslim dilarang mendahulukan kepentingan dirinya di atas kepentingan penghambaan kepada Allah.
Temuan-temuan kontras tersebut mendorong Ayaan untuk semakin yakin meninggalkan Tuhan. Selain mungkin alasan pragmatism lainnya. Tetapi dalam buku yang ditulisnya, Infidel–My Life, keyakinannya meninggalkan Tuhan semakin menguat setelah serangan 9/11 di gedung Pentagon, Amerika Serikat.
Baginya, serangan yang diklaim sebagai terorisme yang mengatasnamakan Islam tersebut bukanlah karena alasan frustasi, kolonialisme, kemiskinan, ataupun Israel, tetapi benar-benar refleksi dari keyakinan keagamaan. Menurutnya, ajaran tentang kebencian, penyerangan dan kekerasan memang terdapat dalam ajaran Islam. Osama bin Laden, seperti halnya Sayyid Qutb yang buku-bukunya pernah Ayaan pelajari, memang mendorong umat Islam untuk melakukan penyerangan, ‘jihad’.
Belajar dari ‘Kekafiran’ Ayaan
Seandainya saat itu Ayaan memiliki teman diskusi keislaman semacam Khaled Abou El Fadl, tentu dia tidak akan mendefinisikan Islam sebagai agama kekerasan dan rasis. Karena menurut pandangan tokoh ini, syariah adalah jalan menuju kebaikan dengan prinsip-prinsip dasar berupa kebebasan, egalitarian, dan keadilan. Pendekatan kritis otoritatif dengan hermeunetik dan analisis teks dalam mengupas hukum Islam yang digunakan Abou El Fadl tentu akan sangat tepat mengimbangi Ayaan muda yang sangat kritis dan penuh tanya.
Jika saja ketika awal masuk Leiden Ayaan tidak hanya mengakses bacaan-bacaan ‘orientalis’, tetapi membaca juga pemikiran-pemikiran Fatimah Mernissi yang, seperti halnya Abou El Fadl, mengkritik hadis periwayatan Abu Bakrah yang dianggapnya bias gender.
Menurut Mernissi, Alquran dan hadis nabi tidak mempertentangkan hak-hak perempuan, hal tersebut terdapat dalam buku karyanya The Veil dan the Male Elite’ yang diterbitkan satu tahun sebelum Ayaan mendarat di Belanda, 1992. Jika itu terjadi, mungkin Ayaan memiliki argumen lebih untuk membela perempuan-perempuan muslim yang menggunakan alasan keagamaan untuk pasrah atas hak-haknya yang terabaikan.
Jika saja konsep mubadalah (kesalingan) yang diperkenalkan oleh Kiai Faqih Abdul Kodir sudah ada ketika Ayaan menyaksikan relasi kerjasama antara Johanna dan suami, dia pasti hanya akan mengkonfirmasi bahwa di agama yang ia yakini juga mengajarkan hal kesalingan demikian. Tetapi sayangnya konsep relasi setara suami-istri dalam Islam tidak ia temukan, justru yang ia dapatkan adalah praktik ketimpangan relasi suami-istri yang didasaran pada ajaran Islam.
Apalagi jika Ayaan mengenal konsep Keadilan Gender Islam (KGI) yang dipopulerkan oleh Nyai Dr. Nur Rofiah, dengan kekritisan dan keberaniannya, Ayaan pasti akan menyuarakan dengan lantang kedudukan perempuan sebagai manusia penuh ciptaan Tuhan. Menggunakan pendekatan KGI, Ayaan akan mampu menolak praktik sunat perempuan yang tidak menimbulkan maslahat bagi perempuan.
Sayang, semua momen-momen negatif yang Ayaan saksikan selalu berbanding lurus dengan teks-teks keagamaan yang ia dapatkan. Tetapi bagaimanapun, meninggalkan Islam dan berbalik menjadi ‘islamophobia’ bukanlah jalan efektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan muslim, seperti yang ia cita-citakan.
Belajar dari kemurtadan Ayaan, semoga semakin banyak aktivis muslim yang menghadirkan nilai-nilai keislaman yang ‘manusiawi’, yang menjadi gerakan ‘kemanusiaan’. Niscaya Islam tidak hanya akan menjadi magnet bagi Muslim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perwujudan kebaikan umat manusia. []
*)Sumber artikel https://neswa.id/artikel/belajar-dari-kemurtadan-perempuan-refleksi-buku-biografi-ayaan-hirsi-ali-part-ii/