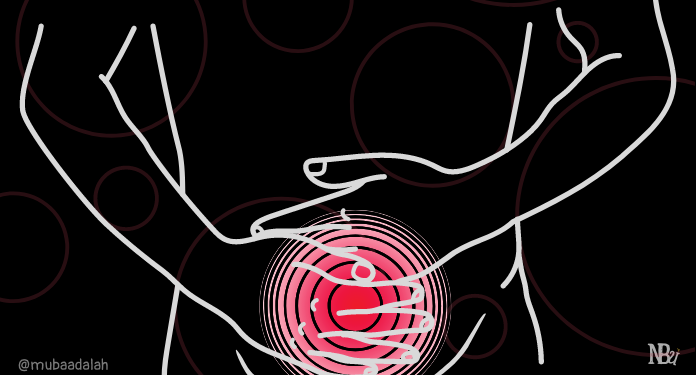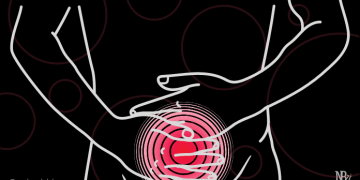Mubadalah.id – Beberapa waktu setelah perhelatan Halaqah Kubra Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 12–14 Desember 2025 berlalu, ada cerita-cerita kecil yang justru terus melekat di ingatan saya. Salah satunya adalah percakapan santai seorang teman dengan rekannya yang kebetulan adalah penyandang disabilitas tunanetra.
Dalam obrolan tersebut, rekannya bercerita tentang kesulitan yang kerap ia alami sebagai perempuan tunanetra, yaitu tentang bagaimana membedakan darah haid dan istihadhah, sementara ia tidak bisa melihat warna darah.
Cerita ini kemudian beririsan dengan refleksi lain yang saya dengar langsung ketika berbincang dengan Bu Nyai Anirah dari komunitas RIPAH (Rumah Inklusi Pahonjean), Cilacap. Dalam percakapan tersebut, Bu Nyai Anirah tidak secara khusus membahas fiqih darah haid, tetapi menyoroti pentingnya isu ini untuk kita bicarakan secara lebih serius dan inklusif.
Menurutnya, persoalan haid dan istihadhah bukan hanya membingungkan bagi perempuan disabilitas, tetapi juga kerap menyisakan kebingungan bagi perempuan non-disabilitas.
Dari dua percakapan yang berbeda itu, saya menarik kesimpulan bahwa persoalan membedakan haid dan istihadhah bukan pengalaman tunggal, melainkan kegelisahan yang nyata dan berulang. Ini akan terasa semakin berat ketika fikih hanya kita jelaskan dari sudut pandang tubuh yang kita anggap “normal”.
Fikih Darah dan Ragam Pendekatannya
Dalam tradisi fikih klasik, pembahasan tentang haid sejatinya tidak terbangun dari satu pendekatan tunggal. Para ulama sejak awal telah memperkenalkan beberapa cara untuk memahami fikih darah haid, mulai dari ciri fisik darah (seperti warna dan teksturnya), batas waktu (minimal dan maksimal haid serta masa suci), hingga kebiasaan atau adat perempuan yang berlangsung secara berulang.
Pendekatan visual melalui warna darah memang sering tersebut dan kerap muncul di bagian awal pembahasan. Warna merah, hitam, keruh, atau kekuningan menjadi salah satu petunjuk untuk membedakan haid dari darah lainnya.
Namun penting kita tegaskan, dalam kitab-kitab fiqih klasik, warna tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan pembahasan tentang waktu dan kebiasaan perempuan. Durasi haid, jarak masa suci, pola yang berulang dari bulan ke bulan, hingga kondisi perempuan yang mengalami kebingungan (mutahayyirah). Semuanya mendapat perhatian yang serius. Ini menunjukkan bahwa fikih darah haid sejak awal menyadari tubuh perempuan memiliki pola dan pengalaman yang tidak selalu sama.
Kritik terhadap Fikih Disabilitas
Persoalan kemudian muncul bukan pada bangunan fikih klasik itu sendiri, melainkan pada cara fikih tersebut sering kita pahami dan diajarkan hari ini. Penjelasan yang seharusnya utuh dan berlapis kerap menyempit dalam praktik pembelajaran. Tidak jarang, kadang yang paling kita ingat hanya satu pendekatan, terutama pendekatan visual melalui warna darah.
Ketika hal ini terjadi, fikih yang sejatinya kaya kemudian tampil seolah-olah sangat bergantung pada apa yang bisa terlihat. Dampaknya terasa bagi perempuan yang tidak memiliki akses terhadap penanda visual, seperti perempuan tunanetra. Bukan karena fiqih menutup ruang bagi mereka, tetapi karena ruang itu jarang ditunjukkan dan dijelaskan secara memadai.
Di sinilah kritik fikih disabilitas perlu kita tempatkan secara proporsional. Kritik ini tidak kita arahkan pada kitab-kitab fikih klasik sebagai warisan keilmuan, melainkan pada kecenderungan kita hari ini. Terutama dalam menyederhanakan fikih dan menonjolkan satu pendekatan sambil mengabaikan pendekatan lain yang sama-sama sah.
Dengan membaca fikih secara lebih utuh, melalui warna, waktu, dan kebiasaan, kita justru menemukan bahwa fikih memiliki kelenturan untuk merespons keragaman pengalaman tubuh perempuan. Termasuk pengalaman perempuan tunanetra yang mengenali tubuhnya bukan melalui penglihatan, melainkan melalui pola waktu dan pengalaman yang berulang.
Fikih Darah; Dari Warna Ke Waktu dan Kebiasaan
Dalam mazhab Syafi’i, warna darah bukan satu-satunya penentu. Imam Syafi’i memberikan perhatian besar pada waktu dan kebiasaan (adat) perempuan. Siklus haid yang berulang dari bulan ke bulan, kapan mulai, berapa lama berlangsung, dan kapan berhenti, menjadi dasar penting dalam menentukan apakah darah yang keluar termasuk haid atau istihadhah.
Artinya, sejak awal fikih sebenarnya sudah membuka ruang bahwa tubuh perempuan memiliki polanya sendiri. Pengetahuan tentang haid tidak semata-mata bertumpu pada apa yang terlihat, tetapi juga pada pengalaman yang terus berulang dan terkenali oleh perempuan itu sendiri.
Jika demikian, menjadikan warna sebagai satu-satunya pintu masuk justru menyempitkan fikih. Ia mengabaikan fakta bahwa tidak semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap penglihatan. Dalam konteks perempuan tunanetra, pendekatan yang terlalu visual bukan hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan keraguan yang tidak perlu dalam beribadah.
Di sinilah pentingnya membaca ulang fikih dengan kacamata keadilan. Bukan untuk meniadakan pendapat ulama, tetapi untuk menempatkannya secara lebih proporsional. Warna bisa menjadi salah satu petunjuk, tetapi bukan satu-satunya. Ketika warna tak bisa terakses, fikih darah haid masih memiliki jalan lain: waktu, kebiasaan, dan pengalaman tubuh perempuan itu sendiri.
Pengalaman yang Berulang; Waktu dan Kebiasaan sebagai Penanda
Bagi perempuan tunanetra, pendekatan ini sangat relevan. Ia mengenali tubuhnya melalui tanda-tanda yang konsisten: nyeri perut, perubahan kondisi fisik, rasa tidak nyaman, perubahan ritme harian, serta waktu datang dan berhentinya perdarahan.
Jika perdarahan datang sesuai dengan siklus bulanan yang biasa ia alami dan berlangsung dalam rentang hari yang sama, maka itu dapat dipahami sebagai haid. Sebaliknya, jika perdarahan muncul di luar kebiasaan, berlangsung lebih lama, atau tidak disertai tanda-tanda tubuh yang biasanya muncul saat haid, maka ia bisa dipahami sebagai istihadhah.
Dalam konteks ini, tubuh perempuan menjadi sumber pengetahuan yang sah. Pengalaman tubuh bukan dugaan, melainkan hasil dari pengamatan yang terus-menerus atas diri sendiri. Pendekatan berbasis kebiasaan ini memberi ketenangan dalam praktik ibadah. Perempuan tunanetra tidak perlu terus-menerus berada dalam keraguan atau merasa ibadahnya tidak sah hanya karena ia tidak bisa melihat warna darah.
Fikih “Seharusnya” Memberi Ketenangan
Membicarakan fikih disabilitas sebenarnya bukan soal membuat aturan baru. Yang lebih penting adalah bagaimana fikih kita baca ulang agar tidak menjauh dari kehidupan nyata, terutama dari pengalaman perempuan yang selama ini jarang didengar.
Ketika mendengar cerita perempuan tunanetra tentang tubuhnya sendiri, kita jadi sadar bahwa fikih tidak selalu gagal, tetapi cara kita memahaminya kadang terlalu sempit. Fikih lalu terasa rumit, bukan karena ajarannya berat, melainkan karena ia tersampaikan tanpa benar-benar mempertimbangkan kondisi orang yang menjalaninya.
Beribadah seharusnya menghadirkan rasa tenang. Bukan rasa kebingungan karena penjelasan agama terasa jauh dari pengalaman sehari-hari. Perempuan tunanetra, sama seperti perempuan lainnya, berhak merasa yakin saat beribadah, tanpa harus terus-menerus meragukan apa yang ia alami. []