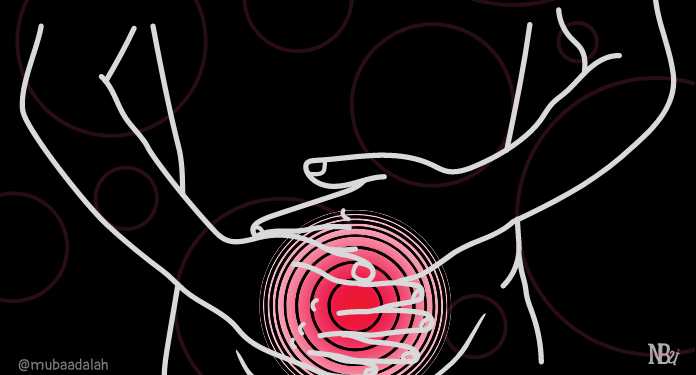Mubadalah.id – Sejak masa awal Islam, persoalan haid, nifas, dan istihadhah telah menjadi tema penting dalam berbagai kajian keagamaan. Para ulama fiqh memberikan perhatian besar terhadapnya, bahkan menulis kitab khusus untuk membahas detail hukum-hukum yang berkaitan dengan tubuh dan pengalaman biologis perempuan.
Di antara mereka adalah Imam al-Haramain dan Abu al-Faraj al-Darimi, yang masing-masing menulis satu jilid besar khusus tentang persoalan ini.
Perhatian besar ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup mata terhadap realitas biologis perempuan. Namun yang lebih penting, sebagaimana dijelaskan oleh Nyai Hj. Badriyah Fayumi dalam Kupipedia.id, ajaran Islam tidak pernah menempatkan perempuan haid, nifas, atau istihadhah sebagai makhluk yang najis atau kotor.
Justru Islam hadir untuk menegaskan bahwa semua proses biologis itu adalah bagian dari kodrat dan rahmat Tuhan yang patut dihormati, bukan disingkirkan.
Fiqh dan Posisi Tubuh Perempuan
Secara umum, fiqh memandang haid, nifas, dan istihadhah sebagai bagian dari kondisi hadats, baik besar maupun kecil. Artinya, seorang perempuan yang sedang haid, kondisinya sama dengan laki-laki yang junub atau orang yang batal wudunya. Yakni ia memerlukan penyucian diri sebelum menjalankan ibadah tertentu.
Dengan cara pandang seperti ini, Fiqh sebenarnya telah menempatkan proses biologis perempuan pada posisi yang terhormat yaitu sebagai bagian dari kehidupan manusia yang wajar dan perlu diatur, bukan dijauhi.
Namun, sayangnya, dalam sejarah panjang penulisan fiqh, tetap muncul pandangan-pandangan yang menyudutkan perempuan haid.
Dalam kitab al-Hayawan karya al-Jahiz, misalnya, menyebutkan bahwa ada empat makhluk yang mengalami haid: perempuan, kelinci, kelelawar, dan anjing hutan. Pandangan ini jelas bermasalah. Menyandingkan perempuan dengan hewan hanya karena kesamaan proses biologis adalah bentuk pemikiran yang merendahkan martabat manusia.
Dalam kitab al-Hawi, haid bahkan menyebutnya sebagai sesuatu yang kotor karena warna dan baunya tidak enak serta membahayakan.
Pandangan seperti ini memperlihatkan bagaimana bias patriarki dan ketidaktahuan medis dapat memengaruhi cara sebagian ulama memandang tubuh perempuan. Mereka gagal memahami haid sebagai mekanisme kesehatan reproduksi, bukan sebagai penyakit.
Padahal, secara medis, darah haid adalah hasil dari proses alami tubuh yang membuang jaringan yang tidak tubuh perlukan. Jika darah itu tertahan, justru akan berbahaya bagi tubuh perempuan. []