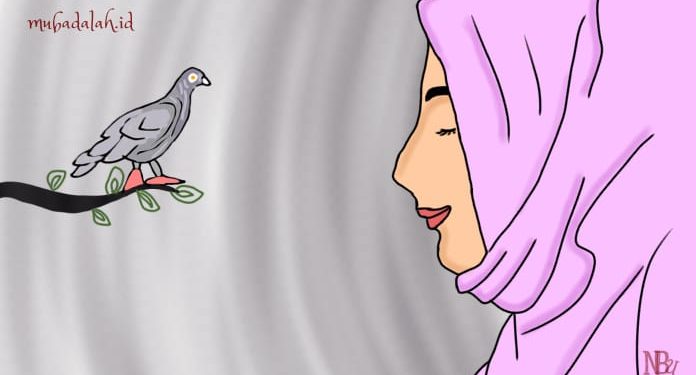“Ratu Saba’ membuktikan bahwa seni memimpin adalah seni mendengar, menimbang, dan memilih jalan terbaik bagi semua.”
Mubadalah. Id. Ketika masyarakat membicarakan kepemimpinan, bayangan yang muncul sering kali masih maskulin: tegas, keras, dan penuh kendali. Gambaran ini membuat kepemimpinan perempuan tampak “tidak biasa”, bahkan kerap dipersoalkan. Padahal, Al-Qur’an justru menghadirkan kisah pemimpin perempuan tanpa nada curiga dan tanpa sikap menghakimi. Kisah Ratu Saba’ menjadi contoh paling jelas.
Al-Qur’an tidak menempatkan kepemimpinan sebagai persoalan jenis kelamin. Ia menempatkannya sebagai soal amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan bukan arena dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan ruang kerja bersama yang saling menguatkan.
Islam dan Prinsip Kesalingan dalam Memimpin
Islam memandang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Dua posisi ini melekat pada laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Tidak ada satu pihak yang memonopoli tanggung jawab moral dan sosial. Karena itu, Islam juga membuka peluang yang sama dalam mengelola kehidupan, termasuk dalam urusan kepemimpinan.
Dalam perspektif Mubādalah, relasi laki-laki dan perempuan tidak bersifat hierarkis, tetapi kolaboratif. Ketika perempuan memimpin, laki-laki tidak kehilangan perannya. Sebaliknya, keduanya bekerja dalam relasi saling melengkapi. Prinsip ini menempatkan kepemimpinan sebagai kerja kolektif, bukan ajang pembuktian superioritas.
Sejarah Islam memperkuat prinsip tersebut. Aisyah r.a. tampil sebagai figur otoritatif dalam ilmu dan kepemimpinan sosial. Ummu Hani mendapat kepercayaan mengelola pasar Madinah. Syajaratud-Durr bahkan memimpin Dinasti Mamluk. Semua contoh ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang kepemimpinan bagi perempuan.
Masalahnya Bukan pada Kemampuan, Tapi…
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang masih mempertanyakan kelayakan perempuan saat mereka memimpin organisasi, komunitas, atau institusi publik. Pertanyaan ini muncul bukan karena kurangnya kapasitas, tetapi lebih sering lahir dari cara pandang lama yang menempatkan perempuan di posisi pendukung.
Perdebatan tentang boleh atau tidaknya perempuan memimpin sering berhenti pada teks, tetapi lupa pada tujuan. Budaya patriarki juga membentuk asumsi bahwa laki-laki pantas berada di depan, sementara perempuan seharusnya berada di belakang. Asumsi ini terus hidup karena diwariskan sebagai “kebenaran sosial”, bukan karena terbukti adil. Akibatnya, perempuan sering harus bekerja lebih keras hanya untuk diakui setara.
Padahal, jika diamati lebih dalam Islam menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama. Pemimpin yang baik membawa aspirasi bersama, bekerja jujur, dan konsisten antara kata dan tindakan, entah datangnya dari perempuan ataupun laki-laki.
Ratu Saba’: Pemimpin Perempuan yang Diakui Al-Qur’an
QS. An-Naml ayat 23 menghadirkan sosok perempuan yang memimpin sebuah negeri besar. Al-Qur’an menyebut bahwa ia memiliki kekuasaan, sumber daya, dan singgasana megah. Yang menarik, Al-Qur’an tidak mempertanyakan fakta bahwa pemimpin itu seorang perempuan. Fokus ayat justru tertuju pada kondisi negerinya yang kuat dan teratur.
Tafsir Fi Ẓilāl al-Qur’an menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah Ratu Balqis, penguasa Kerajaan Saba’ pada masa Nabi Sulaiman a.s. Kisah ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekadar mungkin, tetapi juga nyata dan berhasil.
Al-Qur’an menghadirkan Ratu Saba’ sebagai pemimpin yang eksis, berdaulat, dan berdaya. Narasi ini mematahkan anggapan bahwa kepemimpinan perempuan bertentangan dengan nilai keislaman.
Seni Memimpin ala Ratu Saba’ (Balqis)
Keistimewaan Ratu Balqis tidak hanya terletak pada posisinya, tetapi juga pada cara ia memimpin. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia tidak bersikap reaktif. Ia mengumpulkan para pembesar kerajaan dan mengajak mereka berdiskusi. Ia mendengar, menimbang, lalu memutuskan.
Sikap ini menunjukkan kecerdasan emosional dan politik yang matang. Ratu Balqis memahami bahwa pemimpin yang baik tidak berjalan sendirian. Ia membangun kepercayaan melalui dialog dan musyawarah. Ia memimpin dengan akal sehat, bukan dengan ego.
Sejarah mencatat Kerajaan Saba’ sebagai negeri yang makmur dan damai. Al-Qur’an menggambarkannya dengan ungkapan baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr. Gambaran ini lahir dari kepemimpinan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Relevansi untuk Dunia Organisasi Hari Ini
Kisah Ratu Saba’ terasa sangat dekat dengan realitas organisasi modern. Banyak konflik organisasi muncul karena pemimpin menutup ruang dialog dan merasa paling benar. Kepemimpinan ala Ratu Balqis menawarkan pendekatan berbeda: mendengar sebelum memutuskan, mempertimbangkan sebelum bertindak.
Dalam konteks ini, kepemimpinan perempuan membawa warna penting. Bukan karena perempuan selalu lebih lembut, tetapi karena pengalaman hidup sering membentuk kepekaan sosial dan kemampuan membaca situasi secara menyeluruh. Organisasi yang sehat membutuhkan keragaman cara pandang, bukan keseragaman suara.
Mubādalah mendorong organisasi untuk melihat kepemimpinan sebagai ruang kerja bersama. Perempuan dan laki-laki saling menguatkan, bukan saling menyingkirkan. Bahwasanya kepemimpinan tidak boleh berhenti pada wacana. Pemimpin harus hadir, bekerja nyata, dan bertanggung jawab. Ukuran ini berlaku untuk siapa pun, tanpa melihat jenis kelamin.
Kepemimpinan sebagai Amanah Bersama
Kisah Ratu Saba’ mengajak kita mengubah cara pandang. Kepemimpinan bukan soal siapa yang lebih berhak, tetapi siapa yang mampu menjalankan amanah dengan adil. Dalam semangat Mubādalah, keberhasilan perempuan memimpin juga menjadi keberhasilan laki-laki yang bersedia berjalan bersama.
Dari Ratu Saba’, kita belajar bahwa seni memimpin terletak pada kebijaksanaan, dialog, dan keberpihakan pada kebaikan bersama. Pelajaran ini tetap relevan, dari masa kenabian hingga dunia organisasi hari ini. []