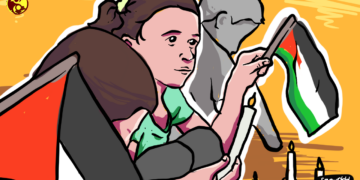Mubadalah.id – Washington DC di musim gugur menjadi saksi bisu perjalanan intelektual sekelompok anak muda Indonesia. Trip akademik yang include program short course selama delapan hari ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah upaya menelusuri jejak Islam Wasathiyah di jantung negara adidaya.
Rute perjalanan kami telah dirancang sedemikian rupa. Setiba di bandara Dulles Virginia, kami berkunjung ke International Institute of Islamic Thought (IIIT). Ini merupakan institute Islam perawat pemikiran Ismail Raji al-Faruqi.
Perjalanan berlanjut dengan sowan ke ADAMS Center (All Dulles Area Muslim Society) yang merepresentasikan komunitas Muslim Amerika yang dinamis. Setelah itu kami mampir ke base camp kita sebagai muslim Indonesia, yaitu Indonesian Muslim Association in America (IMAAM Center) yang menjadi bukti daya tahan identitas keindonesiaan di perantauan.
Namun, di antara rangkaian kunjungan itu, puncak dari semua perjalanan adalah pertemuan dengan seorang legenda hidup: Professor Seyyed Hossein Nasr.
Di pojok ruang Resto yang sederhana namun sarat makna, sang professor yang karyanya telah membentuk wacana intelektual Muslim global menyambut kami dengan keramahan yang khas. Dalam dialog yang berlangsung intens ini, semua kunjungan kami ke institusi sebelum dan sesudahnya menemukan konteks dan jalinan yang monumental.
Sang Sage: Dari Realitas Sains ke Filsafat Yang Membumi
Pria kelahiran Tehran 87 tahun silam, ini memulai ceritanya dengan latar belakang yang mengejutkan. “Saya adalah lulusan terbaik di bidang fisika dan matematika,” ungkapnya dengan senyum yang mengandung makna.
Namun, jalan hidupnya berbelok arah dari laboratorium sains menuju perpustakaan filsafat dan tasawuf. Apa yang tampaknya merupakan perubahan haluan yang drastis, justru menjadi fondasi dari seluruh pemikirannya: bahwa sains tanpa spiritualitas adalah ibarat kapal tanpa nahkoda.
Pada era 1960-an, ketika istilah “krisis lingkungan” masih asing di telinga dunia, Prof. Seyyed Hossein Nasr mencoba bersuara sekaligus berseru lantang tentang hubungan yang terputus antara manusia dan alam. “Saat itu, hampir tak ada yang mau membicarakan krisis lingkungan sambil serius mendalami teologi,” kenangnya.
Karyanya, The Encounter of Man and Nature (1968) dan Religion and the Order of Nature (1996), menjadi yang pertama kali membahas akar krisis lingkungan sebagai krisis spiritual; sebuah perspektif yang revolusioner pada masanya.
Awalnya, pemikiran ini bagaikan suara berteriak di padang gurun. Namun, lambat laun, benih-benih pemikirannya mulai tumbuh. Negara negara Muslim seperti Iran, Mesir, Syria, dan Pakistan mulai menunjuk menteri atau wakil perdana menteri yang fokus menangani lingkungan.
Kebijakan ini bukan sekadar ikut tren global, melainkan sebuah kesadaran yang lahir dari pengakuan bahwa memelihara alam (hifzh al-bi’ah) adalah bagian dari amanah ketuhanan (khilafah), bukan semata mata masalah teknologi atau regulasi.
“The Study Quran”: Sebuah Mahakarya Melawan Arus
Salah satu sumbangsih terbesar Prof. Nasr yang menjadi bahan diskusi kami saat itu adalah kepemimpinannya dalam penyusunan The Study Quran: A New Translation and Commentary. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia bercerita tentang motivasi di balik karya monumentalnya itu.
“Banyak terjemahan dan tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Inggris pada masa itu masih terpengaruh oleh pemikiran modernis abad ke-19 dari Eropa,” jelasnya. Paham seperti evolusionisme dan Darwinisme telah menyusup ke dalam penafsiran, mengaburkan makna otentik dari wahyu. Dalam menghadapi tantangan ini, Prof. Nasr memilih untuk tidak mengutuk atau menolak, melainkan menawarkan alternatif yang lebih substantif.
“The Study Quran” yang terbit pada 2015 itu dirancang dengan tiga pilar utama. Pertama, berakar pada tradisi (rooted in tradition), dengan menggali khazanah tafsir dari mazhab madzhab Islam yang otentik, dari era klasik hingga guru guru beliau sendiri.
Kedua, bahasa yang indah dan menyentuh, menggunakan kekayaan bahasa Inggris untuk menyampaikan kedalaman makna Al-Qur’an tanpa mengorbankan akurasi. Ketiga, kelengkapan dan keakuratan, menjadi rujukan komprehensif yang dengan tegas memisahkan antara penafsiran ulama dengan pemikiran modern.
Karya setebal 2.048 halaman ini menuai sambutan luas, bahkan di kalangan non Muslim. Namun, ia juga mengakui pernah mendapat tentangan. “Sempat dilarang beredar di toko buku universitas tertentu di Arab Saudi,” ujarnya, “tentu alasannya karena mengandung perspektif Sufi yang dianggap menyimpang.”
Pengalaman ini menggarisbawahi pesannya: bahwa menghidupkan kembali khazanah intelektual Islam yang hampir punah adalah perjuangan yang tidak pernah mudah.
Merajut Benang Merah: Pesan Sang Guru untuk Generasi Sekarang
Di penghujung pertemuan yang berharga itu, Prof. Nasr meninggalkan pesan yang menyentuh relung terdalam kesadaran kami sebagai generasi Muslim washatiyah. “Umat Islam hari ini menghadapi dua masalah besar,” katanya dengan nada serius. “Pertama, dunia pemikiran (intelektual) kita sangat lemah. Kita seringkali belajar tentang tradisi kita sendiri justru dari sarjana Barat, bukan dari sumber aslinya dalam bahasa Arab dan konteksnya yang tepat.”
Kedua, lanjutnya, identitas kita sebagai Muslim terletak pada konsistensi antara ilmu dan amal. “Kita harus memiliki fondasi akidah yang kuat. Kekuatan kita adalah pada ketundukan kita (aslam) kepada Allah, dan itulah yang membentuk hubungan (relationship) kita dengan-Nya, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta.”
Pesan ini menghubungkan semua titik dalam perjalanan kami. Berkunjung ke IIIT, kami melihat upaya sistematis untuk melahirkan pemikiran Islam yang kontemporer namun tetap berakar. Berkegiatan di ADAMS Center, kami menyaksikan praktik nyata komunitas Muslim yang inklusif, produktif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Amerika. Dan di IMAAM Center, kami merasakan semangat untuk terus menjaga identitas keindonesiaan sekaligus menjadi penyejuk di perantauan.
Dialog dengan Prof. Seyyed Hossein Nasr menjadi puncak dari semua itu. Beliau adalah bukti hidup bahwa Islam Wasathiyah bukanlah Islam yang lemah secara intelektual atau taklid buta. Sebaliknya, ia adalah Islam yang justru berakar kuat pada khazanah tradisinya, berwawasan global, penuh kesantunan, dan memiliki kepedulian yang syumul pada seluruh ciptaan Tuhan.
Wasathiyah Sebagai Jalan Tengah Yang Kokoh
Perjalanan kami bukan sekadar kunjungan akademis, melainkan sebuah pengalaman transformatif. Kami pulang dengan sebuah kesadaran baru, bahwa untuk menjadi moderat (wasathiyah), kita harus memiliki fondasi keilmuan yang kokoh. Untuk memahami Barat, kita justru harus mengenal diri dan warisan intelektual kita sendiri dengan lebih baik.
Islam Wasathiyah yang kami saksikan di Amerika bukanlah Islam yang tercabut dari akarnya, melainkan Islam yang justru menemukan kekuatannya ketika ia mampu berdialog dengan peradaban modern tanpa kehilangan jati dirinya. Inilah pelajaran terbesar dari sang bijak bestari, Seyyed Hossein Nasr: bahwa di era yang penuh dengan polarisasi ini, jalan tengah yang berlandaskan ilmu dan spiritualitas justru merupakan pilihan paling radikal tetapi transformatif. []