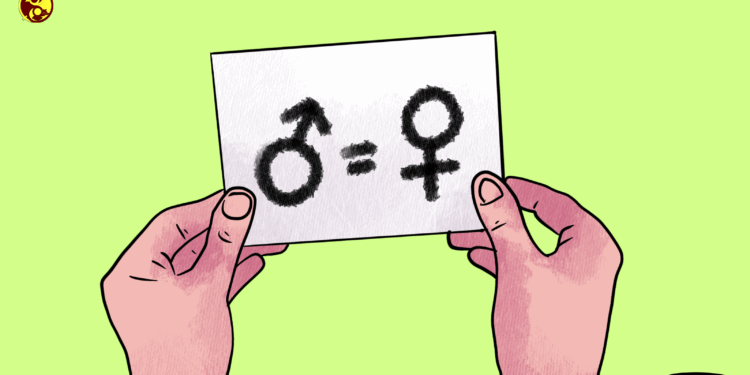Mubadalah.id – Pernahkah kita bertanya, mengapa meski pembangunan telah berjalan berpuluh tahun, ketimpangan dan ketidakadilan gender tetap membayangi? Padahal, berbagai kebijakan telah terumuskan, pelatihan digelar, dan jargon kesetaraan begitu sering kita kumandangkan. Namun, nyatanya, sebagian besar perempuan masih belum merasakan dampak pembangunan yang setara dengan laki-laki.
Apa yang salah? Ataukah ada sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami? Realitanya, pembangunan selama ini terlalu sering melupakan satu hal mendasar: bahwa gender bukan sekadar jenis kelamin biologis, tetapi konstruksi sosial yang menyatu dalam tatanan ekonomi, budaya, bahkan politik. Jika ini tidak dipahami sejak awal, maka setiap kebijakan, sebaik apa pun, akan berpotensi timpang dan bias.
Tulisan ini mengajak kita menggali lebih dalam: bagaimana masa depan gender sebagai konstruksi sosial membentuk ketimpangan struktural? Bagaimana sejarah perjuangan kesetaraan telah bertransformasi, dan mengapa pengarusutamaan gender bukan hanya tuntutan moral, tetapi keniscayaan dalam desain pembangunan masa depan.
Gender, Bukan Sekadar Laki-laki dan Perempuan
Banyak yang masih menyamakan gender dengan jenis kelamin. Padahal, keduanya sangat berbeda. Jenis kelamin adalah kodrat biologis, sementara gender adalah hasil konstruksi sosial yang melekatkan peran, atribut, dan ekspektasi tertentu kepada laki-laki maupun perempuan. Misalnya, anggapan bahwa perempuan sebaiknya tinggal di rumah dan laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama adalah contoh nyata dari konstruksi sosial gender.
Konstruksi ini memengaruhi peluang ekonomi, sosial, dan budaya bagi perempuan. Dalam konteks pekerjaan, perempuan lebih banyak mengisi sektor informal, menerima upah lebih rendah, dan sering kali tidak diakui dalam sistem perlindungan sosial. Sementara itu, kerja-kerja domestik perempuan—yang tak dibayar—dianggap “bukan pekerjaan”. Ini memperkuat ketimpangan dan menciptakan siklus ketidaksetaraan.
Yang lebih mengkhawatirkan, konstruksi gender ini juga berdampak pada akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ruang partisipasi publik. Ketika perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang lebih lemah, lebih emosional, atau kurang rasional, maka segala bentuk partisipasi mereka menjadi termarginalkan—baik secara halus maupun terang-terangan.
Maka jelaslah, memahami gender sebagai konstruksi sosial bukanlah sekadar teori. Ia adalah kunci untuk membongkar ketimpangan struktural yang telah mengakar begitu dalam. Tanpa pemahaman ini, kita akan terus mengulang kebijakan yang hanya menyentuh permukaan, tanpa pernah menyentuh akar masalah.
Evolusi Inklusi Sosial
Perjalanan wacana kesetaraan gender dalam pembangunan tidaklah instan. Pada tahun 1970-an, muncul pendekatan Women in Development (WID) yang mencoba “menyisipkan” perempuan ke dalam arus pembangunan. Namun pendekatan ini masih bersifat aditif—seolah perempuan hanyalah tambahan dari agenda pembangunan yang maskulin.
Memasuki tahun 1980-an, pendekatan berubah menjadi Women and Development (WAD), yang mulai menyoroti ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Lalu di era 1990-an, lahirlah pendekatan Gender and Development (GAD), yang lebih progresif. GAD tidak hanya fokus pada perempuan, tapi juga mempermasalahkan sistem sosial yang menyebabkan ketimpangan gender.
Kini, kita berada pada era Gender Equality and Social Inclusion (GESI). Pendekatan ini menekankan pada dua hal sekaligus: kesetaraan gender dan inklusi sosial. Artinya, pembangunan tidak hanya perlu memikirkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga memastikan kelompok marginal lainnya (seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin) ikut terlibat dan diuntungkan.
GESI lahir dari perjalanan panjang dan refleksi kolektif atas kegagalan pendekatan-pendekatan sebelumnya. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan yang tidak inklusif adalah pembangunan yang timpang dan pada akhirnya, akan gagal mengangkat martabat semua manusia.
Dimensi Ketimpangan
Ketimpangan gender bukanlah isapan jempol. Ia nyata dan terjadi di banyak dimensi. Salah satu yang paling krusial adalah kesehatan reproduksi. Banyak perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, termasuk dalam perencanaan keluarga, layanan ibu hamil, dan penanganan kesehatan reproduksi lainnya.
Dimensi kedua adalah pemberdayaan. Perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan—baik dalam rumah tangga, komunitas, maupun kebijakan publik. Mereka juga menghadapi kekerasan berbasis gender yang merenggut rasa aman dan martabatnya. Padahal, pemberdayaan adalah jantung dari kesetaraan.
Ketiga, pasar tenaga kerja. Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal, dengan perlindungan hukum yang minim dan risiko eksploitasi yang tinggi. Meski mereka berkontribusi besar terhadap perekonomian, kontribusi ini sering kali tak terlihat dalam statistik pembangunan nasional. Ini adalah bentuk ketimpangan yang paling kasat mata sekaligus paling sering diabaikan.
Ketimpangan-ketimpangan ini berdampak langsung terhadap hasil pembangunan. Pembangunan yang tidak memperhatikan dimensi ini akan menghasilkan kesenjangan yang makin lebar. Maka, mengatasi ketimpangan gender bukanlah urusan moral semata, tetapi juga strategi pembangunan yang cerdas.
Pengarusutamaan Gender dan Urgensi Care Economy
Indonesia sejatinya tidak kekurangan kerangka hukum. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu tonggak penting. Namun, implementasinya penuh tantangan. PUG membutuhkan proses panjang dan komitmen lintas sektor. Banyak pihak belum benar-benar memahami esensi dan urgensi dari pendekatan ini.
Dua langkah sederhana namun sangat strategis untuk mempercepat implementasi gender equality adalah memastikan anak perempuan mengakses pendidikan secara penuh dan serius mengakui serta mendukung care economy. Anak perempuan yang sekolah tinggi lebih mungkin menjadi agen perubahan, pemimpin, dan motor pembangunan.
Sementara care economy—terutama pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang banyak dilakukan perempuan—adalah sektor yang sangat penting tapi tak diakui secara ekonomi. Padahal, jika separuh SDM Indonesia yang adalah perempuan tidak diberdayakan dan terus dibebani kerja tak dibayar, maka mereka akan menjadi beban pembangunan, bukan pendorongnya.
Bayangkan jika seluruh kerja domestik perempuan dihitung sebagai kontribusi PDB—angka pertumbuhan ekonomi akan melesat. Tetapi lebih dari itu, pengakuan terhadap care economy akan menempatkan perempuan pada posisi yang setara, dan bukan sekadar pendukung bayangan pembangunan.
Epilog
Pembangunan tidak akan pernah benar-benar berhasil jika separuh dari populasinya tertinggal. Kesetaraan gender dan inklusi sosial bukan hanya soal keadilan, tetapi soal kecerdasan dalam membangun bangsa. Kita tidak sedang membicarakan isu perempuan semata, melainkan fondasi masa depan yang lebih adil, produktif, dan manusiawi. []