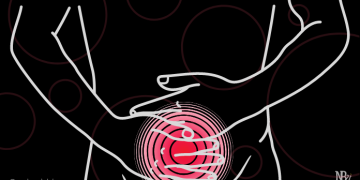Mubadalah.id – Kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di Gowa, Sulawesi Selatan, pada 3 Desember 2025, menyita perhatian publik.
Mengutip laporan Detik.com, korban mengalami kekerasan seksual disertai penganiayaan berat. Ia dipukul hingga wajahnya lebam, bahkan matanya tak dapat dibuka akibat luka yang dideritanya.
Kekerasan itu begitu brutal, hingga memicu kemarahan luas di media sosial. Banyak orang bereaksi dengan marah, kasihan dan emosi.
Namun, kasus ini tidak berhenti pada penderitaan korban. Kisahnya berlanjut ke arah yang lebih parah. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap warga di Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu.
Ia disebut-sebut juga meresahkan warga dan melakukan pencurian. Situasi pun memanas. Alih-alih menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum, warga memilih main hakim sendiri. Pelaku dianiaya hingga meninggal dunia, bahkan jasadnya diseret keliling kampung. Rekaman peristiwa itu tersebar luas, menambah daftar panjang kekerasan.
Peristiwa ini memunculkan banyak perdebatan. Ada yang mengecam keras aksi brutal warga, ada pula yang justru membenarkannya. Namun, jika kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kasus Gowa sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar kemarahan massa atau kebiadaban pelaku. Ia semakin menegaskan bahwa perlindungan bagi perempuan disabilitas di negeri ini masih sangat minim.
Sangat Rentan
Sejak lama, perempuan berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Tetapi ketika perempuan itu adalah penyandang disabilitas, kerentanannya berlipat ganda. Mereka sering dipersepsikan lemah, tidak berdaya, bahkan dianggap tidak mampu melawan atau bersuara.
Pandangan inilah yang membuat perempuan difabel kerap menjadi sasaran empuk untuk melakukan kekerasan seksual. Pelaku tahu persis bahwa korban berada dalam posisi yang sulit membela diri dan kecil kemungkinan mendapat perlindungan cepat.
Kekerasan terhadap perempuan disabilitas sangat berakar pada cara pandang sosial yang keliru. Banyak perempuan difabel kesulitan mengakses bantuan ketika kekerasan terjadi.
Pasalnya, tidak semua kantor polisi memiliki mekanisme ramah disabilitas. Tidak semua tenaga medis memahami kebutuhan korban dengan keterbatasan sensorik, intelektual, atau fisik. Bahkan untuk sekadar melapor, korban sering kebingungan harus ke mana dan kepada siapa.
Artinya, mereka yang paling membutuhkan perlindungan justru sering kali paling tidak terlindungi.
Di sisi lain, reaksi masyarakat yang memilih menghakimi pelaku dengan kekerasan menunjukkan runtuhnya kepercayaan terhadap hukum. Banyak warga merasa menyerahkan pelaku kepada aparat tidak menjamin keadilan akan mereka tegakkan.
Ketidakpercayaan ini melahirkan tindakan yang sangat berbahaya—kekerasan mereka balas dengan kekerasan. Alih-alih menyelesaikan masalah, tindakan ini justru memperpanjang rantai kekerasan dan menjauhkan kita dari solusi yang adil dan manusiawi.
Kasus Gowa memperlihatkan dua kegagalan sekaligus. Pertama, kegagalan negara melindungi perempuan disabilitas dari kekerasan.
Kedua, kegagalan sistem hukum membangun kepercayaan publik sehingga masyarakat memilih bertindak sendiri. Dalam situasi seperti ini, korban perempuan disabilitas kembali terpinggirkan.
Minimnya Ruang Aman
Selama ini, isu disabilitas sering dibahas sebatas soal akses fisik seperti ramp, toilet, atau fasilitas umum. Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendesak dan sensitif, yakni keselamatan perempuan difabel dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, ancaman kekerasan seksual, minimnya ruang aman, dan sulitnya akses pelaporan masih menjadi realitas pahit yang jarang pemerintah bicarakan secara serius.
Peristiwa di Gowa seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Bahwa perempuan disabilitas bukan hanya membutuhkan fasilitas, tetapi juga perlindungan nyata. Mereka butuh sistem pelaporan yang ramah, layanan kesehatan yang inklusif, aparat yang peka, serta masyarakat yang berhenti menyalahkan korban.
Keadilan tidak boleh berhenti pada kemarahan. Keadilan menuntut kehadiran negara yang sungguh-sungguh melindungi yang paling rentan. Jika tidak, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang—dengan korban yang sama, luka yang sama, dan kegagalan yang sama. []