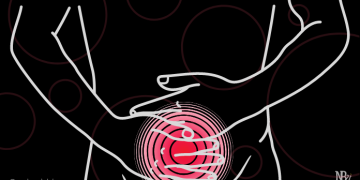Mubadalah.id – Tunanetra bukanlah kelompok yang tidak mampu melihat apa pun. Mereka adalah manusia dengan ragam kondisi penglihatan mulai dari gangguan ringan, berat, hingga kehilangan penglihatan total.
Namun, apa pun tingkatnya, mereka tetap membutuhkan akses yang adil terhadap pendidikan, informasi, dan ruang publik. Salah satu akses terpenting bagi tunanetra adalah Braille, sebuah sistem tulisan berbentuk titik-titik timbul yang dibaca melalui sentuhan jari.
Braille pertama kali dikembangkan oleh Kapten Charles Barbier, seorang perwira militer Prancis, lalu disempurnakan oleh Louis Braille pada tahun 1824. Sistem enam titik dalam sel 2×3 itu terbukti, efisien, dan revolusioner. Berkat Braille, tunanetra bisa membaca, menulis, belajar, dan mengakses dunia secara mandiri.
Namun ironisnya, di Indonesia, Braille justru menjadi barang langka.
Produksi buku Braille membutuhkan biaya tinggi, mulai dari pencetakan khusus, kertas tebal, hingga mesin embosser yang tidak murah. Akibatnya, jumlah buku Braille sangat terbatas. Tidak semua sekolah, perpustakaan, atau lembaga pendidikan mampu menyediakannya. Bahkan, banyak sekolah yang sama sekali tidak memiliki buku Braille.
Akibatnya tunanetra kesulitan mendapatkan bahan bacaan. Literasi mereka menjadi terhambat bukan karena keterbatasan penglihatan, melainkan karena sistem yang tidak menyediakan akses.
Masalah ini bukan persoalan kecil. Data DetikSumut.com mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas tunanetra di Indonesia mencapai sekitar 11 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 300 ribu orang—sekitar 17 persen belum memperoleh pendidikan. Angka ini seharusnya menjadi alarm keras bagi negara.
Kondisi di Ruang Publik
Bahkan, kondisi ini tampak jelas di ruang publik. Sebagian besar penanda arah hampir selalu disajikan secara visual, sementara informasi layanan publik jarang tersedia dalam format Braille atau audio.
Akibatnya, penyandang tunanetra seolah dipaksa beradaptasi sendirian dengan dunia yang sejak awal tidak dirancang ramah bagi mereka. Sedangkan, Braille sendiri adalah hak. Hak atas informasi, pendidikan, dan partisipasi sosial.
Pemerintah sebenarnya sudah banyak menyerukan tentang pentingnya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk tunanetra.
Namun seruan tanpa kebijakan nyata tidak akan mengubah apa pun. Sebab, yang mereka butuhkan adalah keberpihakan anggaran untuk produksi buku Braille. Lalu terdistribusikan ke sekolah-sekolah, serta pelatihan guru agar mampu mengajar secara inklusif.
Lebih dari itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, penerbit, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Bahkan, dunia digital juga harus dimanfaatkan secara serius untuk menyediakan materi bacaan Braille digital dan audio yang mudah mereka akses.
Selama Braille masih sulit tunanetra temukan, maka selama itu juga mereka masih harus berjuang sendiri untuk belajar.
Sebab, aksesibilitas sendiri bukan soal belas kasihan. Ia adalah soal keadilan. Dan Braille adalah salah satu upaya untuk menuju keadilan bagi jutaan tunanetra di Indonesia. []