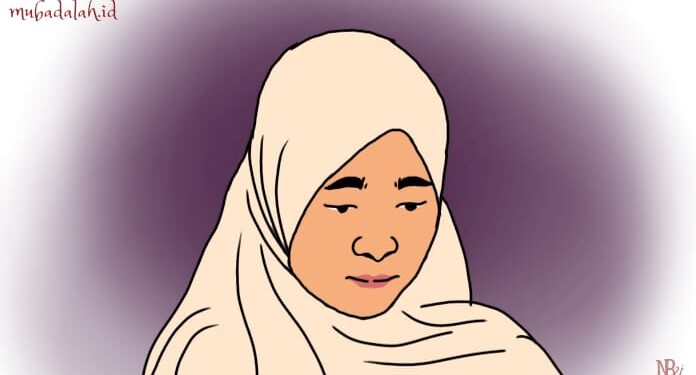“Nah, siapa menurutmu yang paling berhak?”
“Si tukang kayu,” Kata Bulbul
“Si Penjahit,” kata Pangeran Shahzada.
Mubadalah.id – Mereka kembali berdebat untuk ketiga kalinya, perdebatan mereka membuat putri bisu kesal, karena menurut putri bisu kenapa tidak ada yang memikirkan si orang sakti itu. Putri bisupun kembali bersuara, “dasar kalian semua bodoh! Orang sakti itulah yang paling berhak! Karena wanita itu berhutang nyawa padanya.”
Begitulah Mamah membacakan paragraf terakhir dalam dongeng putri bisu. Mama menutup bukunya dan memandang putrinya.
“Bagus ya ceritanya?” kata Mamah. Durroh tidak menjawab, dia memikirkah hal lain.
“Nak, apa kamu menikmati ceritanya?” mamah menyentuh bahu anaknya.
“Ehm, iya suka. Durroh suka ceritanya. Mereka semua cerdas, sang putri cerdas, pangeran juga cerdas, bahkan burung Bulbul juga.” Mamah tersenyum sembari mengelus kepala Durroh.
“Tapi, apa mamah sudah makan?” tangan mamah berhenti membelai rambut Durroh.
“Mamah belum lapar,” jawab mamah, Durroh tidak yakin dengan jawaban mamahnya. Dia tahu mamahnya sudah lapar tapi menunggu ayahnya pulang, mamah ingin makan malam bersama ayah.
“Ayah pulang jam berapa?”
“Sebentar lagi ayahmu pulang, mungkin karena ada kesibukan lain jadi ayah pulang terlambat.” Nada suara mamah dan sorot mata mamah membuat Durroh merasa mamah hanya sedang berbohong di depannya.
“Tidurlah, besok kamu sekolah.” Durroh mengangguk. Mamah menyelimuti Durroh dan mematikan lampu, dia mengelus kening Durroh.
“Durroh bisa tidur sendiri mah,” kata Durroh.
“Ehmm,, anak mamah sudah besar, baiklah, mamah akan menelpon ayah dulu ya.” Durroh mengangguk. “kalau mamah sudah lapar, sebaiknya makanlah.” Mamah tersenyum mendengar nasehat anaknya yang kian tumbuh menjadi semakin baik. “Mamah tutup pintunya ya.” Durroh kembali mengangguk, Durroh melihat Mamah keluar dan menutup pintu kamarnya.
Tak semudah malam malam sebelumnya, sejak kemaren Durroh kesulitan untuk memejamkan mata, langit-langit kamarnya selalu dipandanginya, pikiran anak kecil itu meloncat-loncat penuh tanda tanya. Entah sudah berapa lama dia memandangi langit-langit kamarnya, dia mendengar suara ayahnya datang. Hatinya menyuruhnya untuk diam saja di kamar dan segera tidur, tapi pikirannya menuntun Durroh beranjak dari tempat tidurnya dan membuka pintunya.
“Mas, makanlah dulu, aku sudah memasak makanan kesukaanmu.” Suara mamah sudah mulai terdengar, Durroh melanjutkan langkahnya menuju tangga, dia menuruni beberapa anak tangga dan duduk mendengarkan perbincangan orang tuanya.
“Aku sudah makan. Aku lelah, biarkan aku istirahat.”
“Akan aku buatkan teh hangat.”
“Tak perlu bersikap baik, aku belum memaafkanmu.” Suara ayahnya mulai meninggi.
“Mas, aku tahu kamu kecewa, tapi aku istrimu dan kita saling mencintai. Aku mencintaimu mas.” Durroh melihat mamahnya mencoba memegang tangan ayahnya. Ayah berjalan mendekati mamah, mamah tersenyum tapi selang beberapa detik telapak tangan ayahnya yang besar itu menampar wajah sendu mamah.
“PLAK!”
Durroh menelan ludah, tangannya gemetar, dia takut, dia ingin menangis, tapi dia mengingat kisah peri air mata. Jangan menangis sendirian Durroh, jangan menangis. Begitu kata hatinya.
“Kamu tahu apa yang ada dibenakku setelah mengetahui kebohongan besarmu ini? Aku ingin menikah lagi!”
“Mas, tolong maafkan aku…. Aku juga tidak ingin seperti ini, aku berbohong demi kebaikan semuanya. Mas, aku akan mendidik Durroh sesuai keinginanmu, dia akan menjadi anak pintar, bahkan tidak akan ada yang menandinginya.”
Durroh melihat ayahnya mendorong mamahnya dan terjatuh ke lantai.
“Iya benar, aku menyetujui perjodohan kita yang diatur Mamahku dan aku juga jatuh cinta padamu, tapi bukan berarti kamu bisa berbohong padaku, menyembunyikan sesuatu yang besar ini!” Suara kencang ayahnya dan isak tangis mamahnya membuat Durroh semakin ketakutan.
“Siang tadi rapat pimpinan dan Fauzan mengejekku. Papah mulai tidak mendengarkanku. Kau tahukan? Dulu papah tidak setuju dengan perjodohan ini. Mamahku sudah tidak ada, siapa yang akan membelamu?”
“Kamu mas, kamu yang akan membelaku, aku istrimu, dan kamu suamiku yang akan terus mendukungku.”
Durroh mendengar ayahnya terkekeh.
“Ya, akan aku lakukan itu, kalau kamu bisa hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki.”
“Mas, aku tidak bisa hamil lagi bukan karena keinginanku,” kata mamah, Durroh mendengarnya dan merasakan sesak karena menahan tangis.
“Kalau begitu aku pilih jalan lain, biarkan aku poligami.” Durroh melihat mamahnya terkulai sembari memukul-mukul dadanya.
“Jangan mas, kumohon!”
“Kenapa? kamu tidak mau dimadu?”
“Perempuan mana yang mau suaminya memiliki pasangan lain.”
“Bukankah kamu lebih menguasai kajian agama dari pada saya, kamu alumni pondok pesantren, pasti tahu tentang kasus ini? Saat istri tidak bisa menjalankan kewajibannya seperti tidak bisa melahirkan anak, maka istri harus mengizinkan suaminya menikah lagi.”
“Tidak mas, tidak.”
“Kau tahu, istri shalehah itu yang taat pada suaminya, kamu sudah tidak ingin taat kepada suamimu lagi, heh!?”
Durroh masih melihat mamahnya menggelengkan kepala sembari memegang dadanya.
“Aku pernah mendengar, ada kiai yang memiliki istri lebih dari satu, lantaran istri pertama tidak bisa memiliki anak.”
“Tidak mas, tidak.”
“Aku juga pernah dengar, walau istri pertama tidak setuju, jika suami menikah lagi, maka tetap sah secara agama. Jadi, walau kamu setuju atau tidak, aku akan menikahi perempuan lain yang bisa memberikanku anak laki-laki.”
Durroh melihat tangan mamahnya meraih kaki ayahnya.
“Baik Mas, baik, jika memang itu keinginanmu, aku akan mengizinkanmu menikah lagi.”
Mendengar kalimat mamahnya, Durroh menggigit ibu jarinya dengan sangat kencang, namun dia tidak merasakan sakit.
“Tapi ada dua syarat, entah kamu mau memenuhinya atau tidak, kumohon pertimbangkan lagi.”
“Katakan!”
“Kamu harus membiayai Durroh sampai lulus perguruan tinggi, dan memberikannya jaminan untuk bisa bekerja untuk kemandirian hidupnya. Jangan biarkan dia pergi dari rumah ini. Asuh dia, rawat dia, jaga dia, lindungi dia, jangan biarkan Durroh terluka.”
“Iya, bagaimanapun dia anakku. Dia tidak akan ke mana-mana. Lagian ada kamu yang juga akan menjaganya.”
Durroh melihat Mamahnya mengangguk dan menghela nafas melajutkan kalimatnya.
“Kamu harus tepati janjimu, karena syarat kedua ini akan menentukan komitmenmu.”
“Baiklah, aku berjanji.”
“Syarat kedua, jika kamu sudah menemukan perempuan lain dan memutuskan menikahinya demi ambisimu untuk memiliki anak laki-laki dan menjadi presdir, maka ceraikan aku saat itu juga. Biarkan aku pergi dari hidupmu karena aku tidak akan sanggup melihat lelaki yang kucintai menikahi orang lain.”
Tiba-tiba Durroh menjerit histeris sambil berlari ke kamarnya dan menutup pintu kamar dengan kencang dan menguncinya. Mamah dan ayahnya terkejut.
“Ya Allah, apa Durroh belum tidur?”
Mamahnya langsung berlari ke atas menuju kamar Durroh. Ayahnya masih mematung mendengar persyaratan kedua yang diucapkan mamahnya.
“Durroh… nak, buka pintunya! Durroh ada apa nak, apa kamu belum tidur?”
Tangisan Durroh yang cukup kencang terdengar di telinga mamahnya.
“Durroh, Nak…. Jangan menangis, Nak, buka pintunya!” Suara mamah yang parau membuat Durroh semakin menangis.
***
Zain mendekati Durroh yang sedang duduk sendiri di halaman belakang rumah ayahnya. Setelah pemakaman dan semua orang berangsur pergi, rumah sebesar ini terasa sangat sepi.
“Minumlah ini,” kata Zain.
Durroh melihat gelas berisi susu jahe mengepul, masih panas.
“Terima kasih Kak.”
“Bagaimana perasaanmu?” Zain memulai obrolan.
“Entahlah.”
Beberapa saat mereka saling diam, Durroh menikmati susu jahe buatan Zain. Minuman ini sering diminumnya saat Dia masih tinggal di rumah ayahnya.
“Kuharap kamu sudah tidak membenci ayahmu.”
Durroh tersenyum tipis, “Kau tahu kak, kapan pertama kali aku begitu membencinya.”
Zain menggeleng.
“Saat kamu mengobati luka ibu jariku dan bercerita konyol tentang manusia yang berteman dengan kesedihan.”
Zain mengingat hari itu, di mana pagi buta dia kembali mendengar tangisan anak kecil yang menangis karena melihat ibu jarinya terluka cukup serius, juga kuku yang hampir patah dan kulit yang mengelupas mengeluarkan darah.
“Kau berpikir aku memangis karena lukaku?” Zain mengangguk.
“Sebenarnya luka di hatiku lebih menyakitkan. Malamnya aku mendengar pertengkaran ayah dan mamah. Sejak saat itu aku membenci ayah.”
“Sejak saat itu pula kamu sering mencariku,” kata Zain berusaha menghibur Durroh.
“Gak ya, aku gak pernah mencarimu.”
“Bahkan kamu selalu makan siang di rumahku.”
“Apa aku seperti itu?”
“Dasar,” kata Zain sambil melempar senyum.
“Aku menemukan kehangatan di dalam rumahmu Kak,” lanjut Durroh.
“Lalu kenapa kamu tiba-tiba pergi meninggalkan kita semua?”
Durroh menundukkan kepalanya.
“Kematian mamah, membuatku sangat terpukul. Andai saja ayah saat itu memilih menolong mamah, pasti mamah bisa diselamatkan. Tapi saat itu ayah memilih menunggu istrinya yang mau melahirkan.”
“Karena itu kamu semakin membenci ayahmu dan tidak ingin pulang ke sini.” Durroh mengangguk.
“Kau tahu, saat kau pergi, ayahmu sangat mengkhawatirkanmu, dia mencarimu kemana-mana, bahkan aku juga mencarimu. Kamu bersembunyi di mana sehingga kami tidak bisa menemukanmu.”
Durroh tersenyum.
“Baik ayah maupun Kak Zain, ternyata kalian tidak mengenalku dengan baik sampai tidak bisa menemukanku.”
“Cepat katakan, di mana kamu bersembunyi?”
“Kak, aku tidak pernah bersembunyi, justru saat itu jarakku sangat dekat denganmu.”
Zain kebingungan arah perbincangan Durroh.
“Dekat denganku?” Tanya Zain, Durroh mengangguk.
“Aku nyantri di pesantren Al-Faqih, komplek tahasus selama lima tahun,” kata Durroh.
“Apa?”
Durroh kembali mengangguk.
“Aku memang jarang keluar, dan jika ada acara bareng yang melibatkan semua santri putra dan putri, seperti haul atau khataman, aku lebih memilih di dapur.”
Zain masih terlihat tidak percaya dengan yang dikatakan Durroh.
“Siapa yang mengantarmu ke pesantren?”
Durroh tersenyum, “Ibu Ummi.”
“Ibuku? Jadi selama ini, beliau sudah tahu keberadaanmu.”
“Beliau berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun.”
Zain mengangguk-anggukan kepala padahal dia masih tidak mengerti dengan perkataan Durroh.
“Baiklah ceritakan padaku semuanya, aku harap tidak ada yang terlewat,” kata Zain.
“Kenapa aku harus menceritakan kepadamu?”
“Ya karena aku Zain,” kata Zain.
“Lantas?”
“Dan kau Durroh,” lanjut Zain.
Durroh mengangkat alisnya tidak memahami jawaban Zain. []
(bersambung)