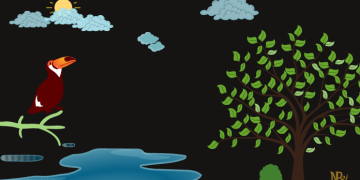Mubadalah.id – Dua hari yang lalu, hujan mengguyur sekitar rumahku. Tak begitu deras, rintik kecil saja. Harusnya tak apa-apa, tetapi ketika sambil memegang gawai dan melihat tangkapan layar media sosial yang mengabarkan tentang korban pengungsian akibat musibah banjir di Sumatra, hujan yang turun menjadi tak biasa lagi.
“Banyak ibu yang belum tidur dua malam. Mereka berjaga karena WC umum gelap dan pintunya susah ditutup.” Berita itu mungkin terdengar datar, tapi saya bisa membayangkan suasananya. Lantai yang masih basah, bau lumpur, dan anak-anak yang menggigil di tikar tipis.
Di media, bencana sering tampil sebagai angka. Jumlah korban, rumah rusak, atau total kerugian. Tapi di lapangan, ia menjelma menjadi keresahan sehari-hari. Perempuan yang menggendong anak sambil menunggu giliran air bersih, lansia yang menahan diri untuk tidak ke toilet karena aksesnya jauh, dan ibu hamil yang tidak tahu kapan bisa periksa kesehatan lagi.
Realitas seperti ini mengingatkan kita bahwa bencana dan krisis iklim tidak pernah netral gender.
Dampak yang Lebih Berat bagi Perempuan
Komnas Perempuan pernah merilis temuan bahwa dampak bencana bisa 14 kali lebih berat bagi perempuan. Angka itu tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari serangkaian faktor sosial yang membentuk ketidakadilan struktural.
Dalam banyak bencana besar, termasuk banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan. Ketika akses air bersih terganggu, misalnya, yang paling tertekan adalah perempuan karena mereka bertanggung jawab pada kebutuhan dasar keluarga.
Ketika jalur evakuasi tidak ramah terhadap mobilitas terbatas, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu dengan bayi menjadi yang paling kesulitan mencapai tempat aman. Masih lekat dalam ingatan, ketika kemarin muncul video pendek di media sosial, seorang bayi kecil yang dievakuasi menggunakan styrofoam kotak.
Data global dari FAO juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin perempuan mengalami kerugian ekonomi lebih besar saat gelombang panas maupun banjir. Hilangnya lahan, tanaman pangan, dan pendapatan sehari-hari membuat banyak perempuan jatuh dalam siklus kemiskinan baru setelah bencana.
Krisis iklim juga terkait erat dengan peningkatan risiko kekerasan berbasis gender. Studi nasional menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan kondisi pengungsian yang tidak aman dapat memicu tingginya kekerasan dalam rumah tangga maupun eksploitasi.
Akar Masalah, Ketimpangan Sosial, Bukan Biologis
Kerentanan perempuan bukan soal “fisik yang lemah”, tapi lahir dari struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang terlindungi. Perempuan sering tidak memiliki aset produktif seperti lahan, sehingga ketika terjadi kerusakan lingkungan mereka kehilangan sumber penghidupan lebih cepat.
Informasi evakuasi dan bantuan sering lebih mudah diakses laki-laki yang lebih bebas bergerak di ruang publik. Perempuan menanggung beban domestik yang meningkat drastis saat bencana. Karena ia harus mengurus anak, air, makanan, dan kesehatan keluarga.
Dalam percakapan di whatshapp grup, seorang ibu korban banjir berkata, “Laki-laki bisa langsung ikut gotong royong atau mencari bantuan. Kami para ibu, harus menunggu di pengungsian sambil menenangkan anak-anak. Rasanya seperti tidak punya pilihan.”
Ketidaksetaraan seperti inilah yang membuat dampak krisis iklim pada perempuan jauh lebih kompleks.
Membaca Krisis Iklim Melalui Perspektif Mubadalah
Dalam pendekatan mubadalah, relasi laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai kerja sama untuk kebaikan bersama. Prinsip ini memberi ruang bagi pemahaman bahwa perlindungan terhadap kelompok paling rentan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas perempuan atau tugas laki-laki semata.
Mubadalah menggarisbawahi pentingnya saling melindungi, saling menguatkan, dan memastikan setiap kebijakan terbangun atas asas kemaslahatan bersama. Jika krisis iklim memperparah ketimpangan gender, maka cara kita merespons pun harus memperbaiki ketimpangan itu.
Perspektif mubadalah menolak melihat perempuan hanya sebagai korban. Ia menekankan bahwa perempuan adalah subjek yang harus terlibat dalam pengambilan keputusan, baik dalam mitigasi, adaptasi, maupun pemulihan pascabencana.
Ini bukan soal “memberi prioritas” secara simbolik, tapi memastikan keadilan berjalan.
Agar respons terhadap krisis iklim lebih manusiawi dan adil gender, ada beberapa langkah yang bisa kita dorong bersama:
Pertama, kebijakan iklim responsif gender. Perempuan dilibatkan dalam penyusunan rencana mitigasi, bukan hanya hadir sebagai penerima bantuan.
Kedua, penguatan ekonomi perempuan. Program pemberdayaan, akses modal, dan pelatihan adaptasi iklim harus menyasar kelompok perempuan yang mengelola pertanian, usaha kecil, atau kerja informal.
Ketiga, pengungsian yang aman dan ramah perempuan. Penerangan cukup, ruang terpisah untuk ibu dan anak, sanitasi aman, serta petugas perempuan sangat penting.
Keempat, pendidikan publik tentang keadilan iklim. Krisis iklim adalah krisis sosial; pemahaman ini harus masuk ke sekolah, komunitas, hingga organisasi keagamaan.
Kelima, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas lokal perlu bekerja bersama dalam semangat saling menjaga.
Merawat Bumi Tanggung Jawab Bersama
Setiap kali bencana datang, kita melihat rumah runtuh dan jembatan hilang. Tapi ada yang lebih sering luput. Bagaimana krisis itu menyasar mereka yang paling tidak punya perlindungan. Perempuan tidak lemah. Mereka hanya hidup dalam struktur yang belum memberi ruang aman. Jika iklim berubah, maka cara kita membangun keadilan sosial pun harus berubah.
Perspektif mubadalah mengajak kita melihat bahwa merawat bumi dan melindungi sesama adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya demi bertahan, tapi demi memastikan masa depan yang lebih adil bagi semua. Terutama bagi mereka, kelompok rentan yang selama ini paling mudah terpinggirkan, tersingkirkan lalu menghilang pelan-pelan. []