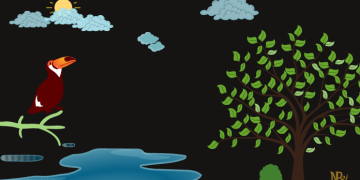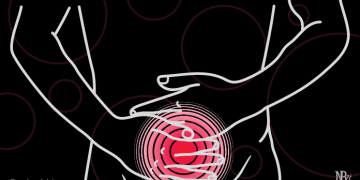Mubadalah.id – Isu keberlanjutan lingkungan hidup kerap menjadi latar wajib dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Di atas kertas, komitmen pemerintah tampak kokoh—dihiasi target hijau, strategi dekarbonisasi, dan janji penguatan hak atas lingkungan yang sehat.
Namun di lapangan, cerita yang tersaji jauh lebih kompleks. Alih-alih menekan laju kerusakan alam, berbagai proyek besar justru meninggalkan jejak deforestasi. Antara lain, konflik agraria, dan ruang hidup masyarakat yang kian terhimpit. Retorika hijau kehilangan makna ketika bumi terus menanggung beban dari ambisi pertumbuhan yang tak mengenal jeda.
Selama satu dekade terakhir, tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat dan petani kecil meningkat seiring ekspansi industri ekstraktif dan proyek pangan berskala besar. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, dalam kurun 2014–2024 terdapat 1.131 orang yang mengalami kekerasan dan kriminalisasi dalam konflik lingkungan.
Dari jumlah tersebut, 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak. Angka itu bukan sekadar statistik, ini menggambarkan luka sosial yang terus terbiarkan menganga oleh kebijakan yang lebih berpihak pada modal daripada manusia dan alam. Keadilan ekologis lagi-lagi di ambang krisis.
Menilik Kebijakan Fiskal Nasional
Kondisi itu kian mengkhawatirkan ketika arah kebijakan fiskal nasional tak mencerminkan prioritas ekologis. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menganggarkan Rp2.996,9 triliun penerimaan negara, terdiri atas Rp2.490,4 triliun dari pajak, Rp505,4 miliar dari PNBP, dan Rp0,6 miliar dari hibah.
Namun, dari total belanja negara Rp3.613,1 triliun, porsi untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya Rp6,2 triliun. Turun Rp1,1 triliun daripada tahun sebelumnya. Di tengah krisis iklim dan kebakaran hutan yang berulang, angka itu terasa seperti menepuk bara dengan ujung jari.
Sementara itu, proyek Food Estate yang mereka gadang sebagai solusi ketahanan pangan justru memperlihatkan sisi gelap pembangunan yang abai terhadap keberlanjutan. Laporan LSM Menelan Hutan Indonesia terbaru mengungkap program ini menargetkan area luas 770 ribu hektare di Kalimantan Tengah, 2 juta hektare di Papua, dan 32 ribu hektare di Sumatera Utara.
Ekspansi itu berisiko memicu deforestasi besar-besaran, dengan potensi kehilangan 1,3 juta hektare hutan di Papua dan 630 ribu hektare di Kalimantan Tengah. Ironisnya, proyek ini terus dijalankan dengan narasi “pangan untuk rakyat.” Padahal yang paling sering kehilangan tanah justru rakyat itu sendiri.
Perspektif Teori Keadilan Lingkungan
Di sisi lain, suara publik menunjukkan arah yang lebih progresif. Laporan Ipsos People and Climate Change (2025) menegaskan 81 persen warga Indonesia merasa kecewa jika individu tak bertindak untuk mengatasi perubahan iklim dan menjadi peringkat kedua tertinggi di dunia setelah Filipina (82%).
Selain itu, 8 dari 10 warga Indonesia mendesak negara agar mengambil peran lebih besar dalam menangani krisis iklim. Jauh di atas rata-rata global (62%) dan tertinggi di Asia Tenggara. Kesadaran publik ternyata lebih maju daripada keberanian kebijakan pemerintah.
Dari perspektif teori keadilan lingkungan David Schlosberg (2007) dalam Defining Environmental Justice, keadilan ekologis bukan hanya soal pembagian manfaat sumber daya alam. Tapi juga pengakuan, partisipasi, dan distribusi risiko secara setara.
Dalam konteks Indonesia, empat prinsip itu nyaris tak berjalan beriring. Masyarakat adat yang menjaga hutan sering kali tak terakui haknya. Partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan kerap hanya formalitas. Sementara risiko bencana ekologis justru paling berat ditanggung kelompok miskin dan rentan.
Situasi ini semakin genting bila menilik data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menunjukkan lebih dari 90 persen bencana di Indonesia tergolong hidrometeorologi. Banjir menjadi yang paling sering terjadi, diikuti angin puting beliung dan longsor.
Membincang Keadilan Ekologis
Dalam sepuluh tahun terakhir, tren ini meningkat akibat perubahan iklim yang memicu curah hujan ekstrem dan pola cuaca tak menentu. Risiko bencana diperparah oleh alih fungsi lahan, urbanisasi tak terencana, dan kerusakan daerah tangkapan air. Ketidakseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan akhirnya menjelma ancaman yang kita undang sendiri.
Kesenjangan antara komitmen dan kenyataan memperlihatkan bahwa krisis ekologis bukan sekadar soal alam rusak, tetapi juga politik keadilan. Pemerintah memang terus menegaskan komitmen terhadap ekonomi hijau, namun arah kebijakan fiskal, proyek pembangunan, dan izin konsesi justru memperdalam ketimpangan ekologis. Saat hutan ditebang untuk tambang, rawa dikeringkan untuk food estate, dan sungai tercemar limbah industri, yang terkikis bukan hanya biodiversitas, tetapi juga keadilan sosial.
Pemerintah perlu berhenti memperlakukan alam sebagai objek ekonomi semata. Sudah saatnya paradigma pembangunan beralih dari eksploitasi menuju pemulihan, dari pertumbuhan menuju keseimbangan. Komitmen terhadap keadilan ekologis harus diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat terdampak, bukan hanya investor.
Keadilan ekologis tidak akan terwujud lewat pidato, melainkan melalui keberanian politik untuk menegakkan batas antara pembangunan dan perusakan. Alam telah memberi peringatan berulang kali, dari asap yang menyesakkan hingga banjir yang menenggelamkan. []