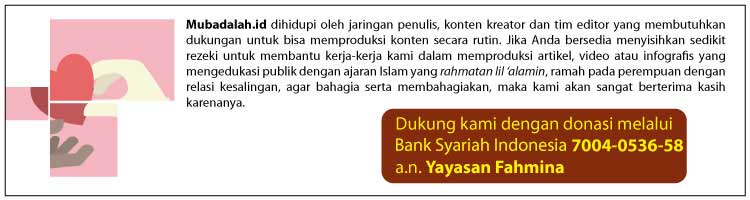Mubadalah.id – Gerakan sosial feminisme gelombang kedua (dan pertama) dinilai sangat eksklusif dan western-oriented. Menurut Maria Mies, perempuan Dunia Ketiga akan kesulitan mengikuti tujuan (wacana) perempuan Dunia Pertama. Apalagi membakukan kurikulum gerakan perempuan melalui kacamata Barat, tentu akan meremehkan perempuan lokal dan mengeluarkannya dari gerakan sosial. Suara-suara kecil dan aktivitas-aktivitas kepedulian akan dianggap reproduksi patriarki, karena menurut “kurikulum feminisme Barat” seperti itu.
Solusinya, identitas harus dilihat sebagai aspek penting untuk memahami sebuah gerakan sosial. Kita tidak bisa memaksakan perempuan suku Badui untuk aktif dalam politik partai atau pengarusutamakan isu gender dan pembangunan. Pun tidak bisa mengeneralisir satu isu di negara Barat—seperti, kuota pekerja perempuan di pertambangan—ke seluruh penjuru dunia. Jika tetap dipaksakan, yang terjadi adalah kolonisasi melalui wacana feminisme.
Artinya, secara ringan, kita harus terlebih dahulu melakukan deforestasi, membangun gedung-gedung pencakar langit, dan mendirikan banyak universitas untuk “mencerdaskan” masyarakat lokal; kemudian menyuarakan “feminisme” menjadi relevan.
Disadari atau tidak, ada biaya mahal untuk “sekadar” mengarusutamakan isu perempuan menurut kurikulum Dunia Pertama. Kita harus (baca: dipaksa), dalam pandangan Angela McRobbie, mengakomodasi kepentingan kapitalisme yang terselip di berbagai lini, seperti pendidikan, pembangunan, reproduksi, dan wacana kebebasan. Dan di saat yang bersamaan, terjadi dehumanisasi masyarakat adat karena mereka dianggap tidak representatif untuk bersuara, kolot dan “anti-kemajuan”.
Maka, perspektif pascakolonial diambil oleh Titiek Kartika dalam bukunya: Perempuan Lokal VS Tambang Pasir Besi Global (2014). Dalam tulisannya, Kartika terpengaruh dan mencoba menguatkan argumen Gayatri C. Spivak, Homi K. Bhabha, Franz Fanon, Mohanty, dan Ong (h. 44-49).
Ia sepakat dengan pendahulunya tersebut, bahwa kolonisasi bisa masuk melalui wacana—tak terkecuali feminisme. Dan, perspektif pascakolonial berusaha, dalam bahasa Derrida, mendekonstruksi wacana kolonial yang telah menghegemoni masyarakat bekas jajahan. Cara yang dilakukan Kartika adalah dengan menerapkan etnografi feminis agar bisa bersinggungan langsung dan mengungkap suara-suara subaltern. Kemudian, mengangkatnya sebagai identitas gerakan sosial feminisme pascakolonial.
Perempuan Adat Melawan Tambang Pasir Besi
Pada dasarnya buku ini adalah disertasi, sebuah penelitian yang dilakukan di Penago Baru, Bengkulu. Masyarakat di sana pernah mengalami percobaan pertanian masa Orde Baru, namun gagal. Kemudian mencoba bermitra dengan PTPN VII untuk menggarap perkebunan sawit, tapi hanya berlangsung 2 tahun. Dan saat ini, warga meneruskan kebun sawit secara mandiri dan tidak terikat dengan perusahaan mana pun. Meski begitu, warga masih menggarap sawah walau mereka sadar kebutuhan air harus bersaing dengan sawit yang boros air (h. 154-157).
Pada tahun 2005, warga mengendus proyek tambang pasir besi dari PT FN yang bakal merenggut 5 desa atau seluas 5.000 hektar. Kesadaran reflektif warga mulai terbentuk, setelah menyadari sulitnya menemukan remis karena aktivitas pertambangan. Sedangkan perempuan mengkhawatirkan anak-anaknya yang terpapar debu proyek karena lalu-lalang kendaraan berat yang keluar masuk tambang.
Gejolak perlawanan gerakan sosial warga meletup. Dari menentang PT FN hingga Bupati dan lembaga legislatif. Aksi-aksi koersif juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan kolektif warga, dan bagaimana posisi perempuan dalam konflik, Kartika menuturkan bahwa perempuan memiliki posisi dalam gerakan sosial yang setara dengan laki-laki. Para perempuan bukan hanya ikut-ikutan aksi karena suaminya, karena ada juga perempuan lain yang juga turut aksi demonstrasi, dan memiliki komando protes perempuan (180).
Kearifan lokal ditunjukkan Kartika sebagai pembentuk identitas gerakan perempuan. Seperti mengenali debu sebagai penganggu tanaman cabai, bahkan membunuhnya. Kemudian perempuan juga mengenali pasir besi sebagai penyaring air untuk menjadi bersih; dan ketika pasir besi dikeruk, perempuan menyadari air menjadi kotor dan keruh karena “alat” saringnya hilang.
Kesadaran kolektif perempuan dalam gerakan sosial tersebut ditransmisikan melalui arisan dan beberapa pertemuan, atau sekadar ketika bertamu. Dari forum-forum kecil itulah perempuan mencetuskan perlawanan dan mencoba berkontribusi terhadap tempat di mana ia berada. Salah satu perempuan militan sekaligus pemimpin gerakan sosial, yang disebut Kartika Mak Jk, bahkan yang menginspirasi suaminya untuk menolak tambang.
Bagi Mak Jk, tambang telah menunjukkan watak serakahnya sejak ia menjalani masa kanak-kanak. Hasil pengamatan sehari-hari, seperti jalanan rusak dan berkurangnya ikan-ikan yang didapat nelayan, merupakan alasan utama kenapa warga harus dikumpukan untuk mengambil sikap melalui gerakan sosial terhadap tambang.
Dengan demikian, perempuan lokal telah menentang wacana global tentang “kemajuan” yang disimbolkan dengan pembangunan. Identitas lokal (nelayan, petani) adalah perspektif utama untuk melihat sebuah tawaran pembangunan. Secara khusus, perspektif perempuan tidak boleh diabaikan. Namun Kartika mengakui, perempuan memiliki akses bicara dan informasi di desa, tapi sayangnya ruang publik yang lebih luas (di luar desa) sulit diakses perempuan (h. 221).
Berbagai keterbatasan akses politik dan bersuara, diatasi perempuan dengan melakukan aksi “ekstrem”. Mengucapkan coarse language, seperti “anjing”, “bajingan”, “keparat”, lalu aksi “tangkap burung” (h. 226)—perempuan di garis depan gerakan sosial dan menangkap penis para polisi untuk membuka jalan bagi demonstran laki-laki—adalah manifestasi puncak kemarahan kelompok subaltern. Sebab, itu ruang yang dimiliki perempuan; dan ketika menemukan ruang itu, perempuan tidak mau menyia-nyiakannya untuk meluapkan suara yang terpendam.
Rujukan untuk Melihat Masyarakat Lokal
Kartika telah membuka mata kita, bahwa perempuan harus dilihat sebagai subyek aktif di dalam masyarakat. Mengakuinya tidak harus menunggu mereka melakukan apa yang dilakukan laki-laki (dalam konteks gerakan). Tetapi harus melihat menggunakan lensa multidisiplin, seperti menakar struktur budaya, gender, geografi, politik, dan akses.
Dengan melihat secara kritis aspek-aspek tersebut, kita akan sukarela mengakui identitas perempuan lokal, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari gerakan feminis—tanpa harus menggunakan term “feminis(me)”.
Meski perjuangan mereka “sekadar” lingkup lokal—tidak semewah wacana “feminisme Barat”—tapi sebenarnya memiliki dampak global: dengan gagalnya tambang pasir besi, maka produksi emisi karbon mampu diredam dan mencegah kerusakan alam semakin meluas. Sedangkan isu feminisme-nya adalah, perempuan Penago memperjuangkan kesehatan reproduksi yang terganggu oleh aktivitas pertambangan. Dan sebetulnya, kerusakan lingkungan adalah isu feminis, dan telah diperjuangkan pula oleh perempuan Penago.
Dengan demikian, buku ini semakin layak dibaca untuk memperluas sudut pandang kita dan mencegah rasa sesumbar sebagai “intelektual”. Jika memang benar-benar intelektual (terlebih peneliti), yang pertama dilakukan ketika “datang” ke masyarakat lokal dan melihat perempuan, adalah mengakuinya sebagai subyek, bukan obyek. Sebab, pengalaman adalah arkeologi pengetahuan perempuan yang bisa ia letupkan sewaktu-waktu demi bertahan hidup. []
Judul Buku: Perempuan Lokal VS Tambang Besi Global
Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Penulis: Titiek Kartika
Tahun Terbit: 2014
Tebal: xxiv + 304 hlm.
ISBN: 978-979-461-892-9