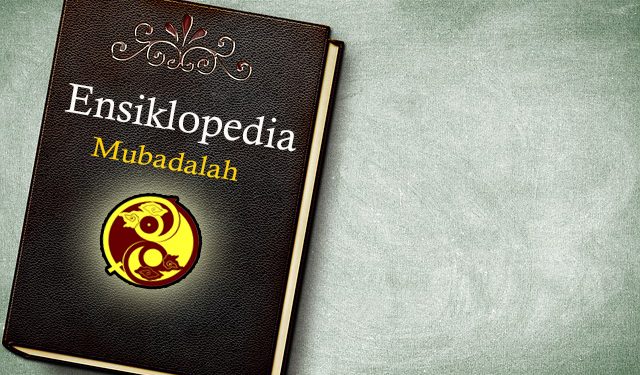Mubadalah.id – Ada banyak ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi antara istri dan suami dalam rumah tangga, yang dipahami secara bias. Seolah-olah setelah menikah, perempuan itu seperti robot, manusia ‘mati’ yang bisa bergerak hanya jika dikendalikan oleh ‘remote’, oleh suami. Domestifikasi istri menjadi bagian yang paling banyak pembahasan.
Seolah-olah Islam menghendaki perempuan yang telah menjadi istri, untuk berhenti atau tidak bekerja sama sekali, untuk fokus di rumah saja mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Istri akhirnya menjadi manusia yang tidak berdaya lagi. Inilah gambaran sederhana yang dimaksud dengan domestifikasi istri. Sebagai upaya ‘merumahkan’ istri.
Padahal Islam yang saya pahami, justru memposisikan kedudukan istri dan suami secara sama dan mulia. Sebelum maupun setelah menikah, istri tidak lantas turun derajat menjadi manusia ‘kelas dua.’
Perempuan itu sebagaimana laki-laki yang telah Allah berikan potensi dan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkiprah sesuai minat dan kemampuannya masing-masing.
Maka sebetulnya yang paling berhak menentukan apakah istri mau menjadi apa (berkiprah di mana) setelah menikah, adalah sang istri sendiri bukan suaminya. Karena istri sepenuhnya adalah makhluk Allah yang berdaulat dan merdeka.
Suami hanya diperkenankan untuk sekadar memberi masukan dan penguatan, bukan malah melemahkan dan melarang-larang.
Termasuk fenomena hijrah yang belakangan ini sedang marak digeluti oleh para perempuan dan istri. Hijrah yang dipahami sebagai komitmen untuk bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi itu oke, tidak ada masalah, patut kita apresiasi.
Tetapi akan menjadi masalah ketika tuntutan hijrah itu menuntut para istri untuk berbusana serba tertutup, hingga puncaknya memakai cadar, sambil rela resign dari pekerjaan dambaannya selama ini.
Saya ingin mencoba merekonstruksi pemaknaan hijrah yang kurang pas ini. Hijrah itu tidak identik dengan berpakaian serba panjang, tertutup sampai kemudian memakai cadar.
Hijrahnya seorang istri juga tidak identik dengan keluar dari pekerjaannya selama ini. Hijrah juga bukan berarti dipahami sebagai komitmen perempuan dan desakan suami untuk beraktivitas di rumah saja.
Sekali lagi, komitmen hijrah dan cita-cita menjadi istri salehah itu sangatlah mulia. Hanya saja kita tidak boleh mempersempit maknanya. Berhijrah dan menggapai predikat istri salehah tetap harus dilakukan dengan ikhtiar yang perlahan, tekun dan sabar. Tak perlu terburu-buru, terpengaruh gengsi atau hanya sekadar ikut-ikutan kebanyakan orang.
Perempuan yang memilih tetap bekerja setelah menikah tidak lantas akan lebih buruk daripada perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan begitupun sebaliknya. Kita harus menghargai pilihan hidup para istri tanpa ada intervensi tekanan maupun paksaan.
Termasuk saya tertarik untuk menyoroti fenomena hijrah para artis. Mereka yang awalnya terlibat banyak waktu di dunia hiburan, dengan alasan hijrah lalu kemudian mereka ‘mendadak’ berubah, mendadak serba Islami, mendadak aktivitasnya penuh dengan pengajian.
Padahal kalau saja mau merenung walau sejenak saja, mereka tetap bisa menjadi artis tanpa harus tiba-tiba meninggalkannya secara drastis. Mereka tetap bisa seperti biasa menjadi artis, menjadi pasangan istri dan suami, sambil terus ikhtiar memperbaiki diri, entah itu melalui ibadah maupun akhlak sehari-hari.
Profesi sebagai artis tidak berarti haram dan lantas harus ditinggalkan. Profesi apapun boleh dan halal digeluti selama dijalankan secara proporsional selama kita tidak meninggalkan kewajiban beribadah.
Berikut juga perlu dipahami bahwa mengurus rumah tangga dan mendidik anak bukanlah tugas mutlak istri seorang diri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan mendidik anak, sudahlah pasti menjadi tanggungjawab bersama antara istri dan suami. Istri dan suami saling berbagi peran. Jadi tidak ada dikotomi pekerjaan, istri di rumah saja sementara suami bekerja di luar.
Perempuan itu sebagaimana laki-laki tetap boleh berkiprah di ranah sosial sekalipun ia telah menikah dan dikaruniai anak. Lagi pula keputusan istri bekerja itu merupakan salah satu wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Suami harusnya bangga jikalau istrinya mampu berkiprah di berbagai ranah publik, entah itu menjadi guru, dosen, polisi, pengusaha, politisi dan lain sebagainya.
Saya merasa perlu menulis catatan ini karena pengaruh budaya patriarkhi terhadap relasi istri dan suami masih bias dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, pastikan bahwa keputusan istri apakah akan tetap bekerja setelah menikah, ataupun hanya menjadi ibu rumah tangga didasari atas dasar kerelaan bukan atas dasar tekanan atau paksaan dari suami.
Kita harus kembali pada prinsip dasar bahwa perempuan dan laki-laki, istri dan suami itu sama-sama mulia, masing-masing berdaulat. Termasuk pemahaman yang kerap mengerdilkan perempuan, bahwa konon katanya perempuan itu tercipta dari hanya tulang rusuk, itu tidak boleh dimaknai secara keliru.
Istilah tulang rusuk itu hanya kiasan, bukan makna sebenarnya, sebagai simbol bahwa istri dan suami itu saling dekat dan saling membutuhkan.
Akhirnya mari kita saling belomba dalam kebaikan. Perempuan dan laki, istri dan suami yang saling mensuport dan berkontribusi dengan sebaik mungkin untuk kepentingan bangsa dan agama.
Sejarah Islam telah mencatat bahwa ada banyak perempuan dan atau istri yang punya kiprah hebat tanpa harus tersandera karena statusnya sebagai istri.
Termasuk misalnya dewasa ini, ada banyak para istri yang mendadak resign dari pekerjaan yang telah lama digelutinya atas alasan ingin berbakti kepada suami dan mengganti kesibukannya selain dengan full mengurus rumah tangga, juga diisi dengan menjalankan bisnis di rumah. Terutama menggeluti bisnis online.
Kalau keputusan tersebut didasari atas dasar agar istri tidak ke mana-mana, supaya istri tidak menjadi fitnah, maka hal itu masuk dalam kategori domestifikasi istri. Wallaahu a’lam.[]